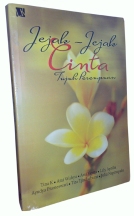Oleh Syaiful Alim
 Data Objek Telaah:
Judul : Konde Penyair Han
Penulis : Hanna Fransisca
Penerbit : KataKita, Depok
Cetakan : 1, April 2010
Tebal : 141 halaman
Data Objek Telaah:
Judul : Konde Penyair Han
Penulis : Hanna Fransisca
Penerbit : KataKita, Depok
Cetakan : 1, April 2010
Tebal : 141 halaman
***
Prolog
Jujur, sebenarnya saya gentar menulis hasil pembacaan saya terhadap buku puisi Konde Penyair Han (KPH) karya Hanna Fransisca ini. Kenapa? Pertama, KPH diberi epilog oleh penyair besar Indonesia, Sapardi Djoko Damono. Kedua, KPH masuk dalam 5 Besar Khatulistiwa Literary Award 2010. Ketiga, KPH meraih penghargaan Buku Sastra Terbaik Pilihan TEMPO 2010.
Selain ketiga faktor di atas, kegentaran saya juga dipengaruhi oleh siapa saya sesungguhnya. Saya bukan sarjana sastra, bukan esais sastra, dan bukan penyair. Secara akademik, saya sarjana syariah yang jauh dari pembahasan sastra dan hal ikhwal yang berkaitan dengannnya. Nah, tetapi kenapa saya berani menuliskan ini?
“Saya punya rencana akan menelaah buku puisi Mbak”
Kalimat yang terucap itulah yang menggedor-gedor jantung saya untuk mencari dan mencuri waktu menulis hasil pembacaan KPH dengan segala kekurangan dan ketaksempurnaan. Saya haturkan mohon maaf kepada penyair Hanna Fransisca dan para pembaca.
Cara Kesatu: Ilalang dan Luka Pengarang
Saya katakan, 67 sajak KPH adalah penjabaran dari ungkapan sejarah hidup penyair yang menghabiskan 9 lembar (hal. 11-19) yang berjudul ‘Konde dan Rambut Saya yang Jelita’. Dari situ, kita memperoleh biografi diri penyair, proses kreatif, dan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang berjasa dalam penerbitan buku puisinya.
Saya yakin bahwa yang ditulis penyair pada halaman-halaman awal buku puisi ini adalah semacam pintu atau bahkan keutuhan ‘rumah’ sajak-sajak dalam KPH ini. Untuk itu, saya akan menyingkap sajak-sajak melalui lorong yang ditunjukkan oleh penyairnya sendiri.
Menurut Aminuddin (2010), bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara kehidupan seorang penyair dengan gagasan yang dituangkan dalam puisi yang diciptakannya. Dia melanjutkan, dengan demikian, dapat juga disimpulkan bahwa manfaat mempelajari biografi pengarang adalah untuk mengembangkan kemampuan apresiasi, dan bukan untuk menghafalkan angka dan tahun.
Sebelum dilakukan telaah bagaimana hubungan antara kepribadian dan karya sastra, terdapat beberapa unsur yang perlu diketahui. Pertama, kita perlu mengamati si pengarang untuk menjelaskan karyanya. Telaah dilakukan terhadap eksponen yang memisahkan dan menjelaskan kualitas khusus suatu karya sastra melalui referensi kualitas latar, kehidupan, dan lingkungan pengarang. Kedua, kita perlu memahami si pengarang terlepas dari karyanya; caranya, kita amati biografi pengarang untuk merekonstruksi si pengarang dari sisi kehidupannya dang menggunakan karyanya sebagai rekaman kehidupan dan perwatakan. Ketiga, kita perlu membaca suatu karya sastra untuk menemukan cerminan kepribadian si pengarang dalam karya tersebut (Abrams, 1997).
Berpijak dari dua pandapat ilmuwan sastra di atas, saya mendapati dua kata kunci untuk menguak sosok penyair dan karyanya, yaitu ilalang dan luka (pengarang). Sebelum diteruskan, ada pertanyaan yang urgen: kenapa Hanna Fransisca memilih ‘sajak/puisi’ sebagai media ungkap kehidupan pribadinya yang sangat personal? Kenapa bukan prosa seperti Anne Frank yang menuangkan kegetiran hidup pada masa rezim Hitler dalam The Diary of Young Girl? Kita tahu, selain itu adalah pilihan Hanna Fransisca, bahwa sajak atau puisi dibentuk oleh beberapa unsur, misalnya unsur diksi, citraan, kiasan, simbol, dan metafora. Nah, unsur-unsur yang saya sebutkan itulah yang menyembunyikan makna atau hakikat yang lain dari sajak. Di satu sisi, penyair Hanna Fransisca ingin berbagi kisah hidup, tetapi di sisi lain, sang penyair mencoba ‘menutupi’ rahasia atau misteri dengan memanfaatkan unsur-unsur puisi yang telah saya sebutkan. Apa yang terjadi? ‘Yang personal’ masih berstatus ‘Yang Sakral’. Mari, kita telusur.
“Sejak kecil saya menyukai kesendirian: memandang rumputan, memperhatikan capung meluruskan sayap seperti pesawat kecil yang meluncur ke angkasa, juga belalang-belalang yang memiliki kaki panjang untuk melompat. Saya juga menyukai warna kupu-kupu, dan sering kali membayangkan bisa terbang dengan sayap warna-warni.
Di belakang rumah saya ada hamparan semak, di depan rumah tak ada bunga-bunga yang bisa ditanam (halaman rumah yang bisa ditanami adalah kemewahan yang tak dimiliki keluarga kami), maka puluhan bunga-bunga liar, serta warna-warna ilalang (yang sering kali berubah setiap musim berganti), menjadi surga bagi kesendirian. Saya sering kali terpesona dengan kerisik angin yang memompa ratusan ilalang, bunyi unggas milik tetangga, burung-burung kecil yang liar, serta binatang-binatang halus yang senantiasa beterbangan ketika malam tiba. Saya selalu membayangkan mereka cukup berbahagia.”
(Konde dan Rambut Saya yang Jelita, hal. 11-12 garis miring dari saya)
Sungguh pengantar yang menggetarkan! Bayangkan, penyair Hanna Fransisca langsung menumbuk jantung pembacanya dengan memaparkan kesendirian masa kecil dan menyebut ilalang sebagai surga bagi kesendiriannya. Bagi saya, inilah awal luka pengarang dan ilalang hanyalah sebagai teknik pengalihan lukanya itu. Ilalang di sini bisa menjadi ‘metafora’ dan bisa berdiri sendiri yang merupa dunia tumbuhan. Mungkin sang penyair ingin mengatakan bahwa hidup adalah setajam ilalang, tetapi memendam pesona.
Pada pengakuan berikutnya, sang penyair makin jatuh cinta pada ‘ilalang’ dan sebenarnya apa yang dimaksud ‘luka’ itu:
“Setiap pagi saya berangkat ke sekolah dengan sepasang sepatu paling buruk. Sungai dan gemericik air yang selalu saya lewati ketika pergi dan pulang adalah keajaiban lain yang tertinggal menjadi ingatan. Gema para perempuan yang mencuci pakaian, suara kain basah yang dibanting di atas papan, serta mulut anak-anak yang berteriak memanggil ibunya. Saya melihat para perempuan, anak-anak, dan sungai jernih yang mengalirkan kehidupan panjang sebagai sesuatu yang mengandung bahagia.
Ketika di rumah, saya selalu dihadapkan terlibat memikirkan persoalan hidup sehari-hari—yang semestinya adalah bagian dari persoalan orang-orang dewasa. Sering kali ketika menghadapi ancaman tidak bisa mengikuti ujian, dan mendengar bagaimana Ibu mengatakan, “Tidak ada perlunya membayar uang sekolah, uang sedikit lebih baik digunakan untuk membeli beras!”, maka saya berdiri sejenak di belakang rumah melihat bagaimana angin begitu kerasnya menghempaskan batang-batang ilalang. Ilalang-ilalang yang kuat, ilalang-ilalang yang selalu kembali tegak berdiri setelah dihempas ke kanan dan ke kiri. Saya akhirnya jatuh cinta pada ilalang. Hingga larut malam saya membantu Ibu mencuci pakaian-pakaian para langganan (Ibu adalah pahlawan sebenarnya, yang mencari pekerjaan tambahan dari upah buruh mencuci), saya selalu tetap kuat berdiri. Saya harus tetap kuat, meskipun saya selalu ingin menangis ketika mendengar derit pintu, dan Ayah pulang pada puncak malam yang lelah dengan suara batuknya yang bergema panjang hingga pagi hari. Saya selalu bermimpi menjadi ilalang.”
(Konde dan Rambut Saya yang Jelita, hal. 12-13 garis miring dari saya)
Ternyata luka itu bermula dari getir takdir atau nasib yang salib. Dan yang mengejutkan adalah ilalang kini seolah hidup; ilalang telah jadi pembasuh luka pengarang. Inilah keistimewaan sajak-sajak Hanna Fransisca dalam KPH ini selain ia pandai memanfaatkan dunia kuliner untuk menghidangkan ‘bebek peking’ kalau meminjam bahasa Sapardi Djoko Damono. Benda-benda mati atau hidup diusung ke dalam sajak-sajaknya tanpa tergelincir pada kerumitan berbahasa. Coba kita tengok bait-bait sajak yang diniatkan sebagai ode kepada sang Ibu Chang Po Cin dan sang Ayah Cu Kim Chan.
Adik, sebutir nasi
yang menyelinap di lambungmu,
adalah bulir-bulir lepuh tangan ibu.
(sebait sajak ‘Layang-layang’ hal. 38)
Ini kacang hijau
atau hatimukah,
yang kami makan hari ini,
bersama Tuhan yang selalu
kuajak
bicara.
(sebait sajak ‘Puisi Kacang Hijau’ hal. 90)
Ayah yang lelah, membisikkan kata sayang begitu pasrah,
lalu menggiringnya pergi
menjadi tiada.
(bait terakhir sajak ‘Kepada Kerbau’ hal. 60)
Sengaja bait-bait di atas saya biarkan begitu saja, saya telaah di waktu dan tempat pembahasan yang tepat. Nah, untuk mengakhiri tulisan bagian pertama ini, sila dinikmati kelanjutan pengantar buku puisi KPH.
“Saya kira pada waktu-waktu yang paling buruk itulah saya menulis puisi. Saya kira bukan puisi, tapi hanya semacam puisi. Saya menulis catatan keluh-kesah dengan diam-diam, menyembunyikannya dengan diam-diam dalam buku tulis, dan tak seorangpun boleh tahu. Saya adalah anak perempuan pemalu yang tak pernah memiliki keberanian untuk berbicara, tak pernah memiliki keberanian untuk memulai berteman, atau untuk bertanya soal apa saja kepada siapa saja. Maka saat menulis saya memiliki tempat paling nyaman untuk berbicara. Pada zaman buruk itu pula, saya kira, awal perkenalan saya dengan membaca. Saya menyukai buku cerita yang awalnya diperkenalkan ibu guru di perpustakaan sekolah. Saya suka membaca cerita, karena di dalamnya saya bisa mendengar sekaligus berbicara. Saya menyukai cerita, karena di sanalah saya bisa mengunjungi tempat-tempat bahagia. Saya bisa berteman dengan tokoh-tokoh di dalamnya, mengajak mereka berbuat apa saja di luar buku—di dalam imajinasi saya. Itulah saat-saat paling indah, di samping keindahan berteman dengan ilalang dan bunga-bunga liar, sungai dan burung-burung, juga kupu-kupu dan ratusan serangga yang senantiasa berlesatan memburu cahaya di malam hari.
Lalu datanglah saat paling memalukan dalam hidup saya, yakni ketika ibu guru yang mengetahui saya menyukai buku cerita. Beliau menyuruh saya membaca puisi di depan kelas. Demi Tuhan saya membenci hari itu. Seumur hidup saya tak pernah membayangkan harus berdiri di depan kelas dan berbicara. Saya lalu berdiri di depan kelas dengan gagap dan nyaris pingsan (disoraki teman-teman). Saya berdiri terpaku, gemetar, tak bisa berkata apa pun, dan kemudian menangis.
Saya terus menulis yang bukan puisi, di dalam buku yang selalu diam tapi sesungguhnya mengajak saya bicara. Saya selalu katakan bukan puisi, karena sejak hari memalukan itu, saya membenci puisi. Tentu saya tetap suka membaca cerita, karena buku-buku cerita sudah jelas bukan puisi. Hingga kemudian saya berhenti sekolah (saya hanya lulus sekolah formal setingkat SMP), dan kemudian menjadi pelayan toko.
Demikianlah hidup semakin rumit, karena saya sadar bahwa perjuangan hidup ternyata bukan cerita. Dengan melewati sejarah kejam bertubi-tubi, memintas usia remaja di lorong-lorong ruko, saya jadikan seluruh umur dan keremajaan saya adalah kerja. Barangkali karena takdir saya sebagai perempuan pemalu yang tak pernah jatuh cinta pada usia remaja (yang selalu berbicara pada saat-saat sendiri), maka di sela-sela tumpahan waktu untuk kerja, saya selalu membutuhkan buku-buku. Buku-buku itulah, yang kelak secara ajaib telah membuka kotak pandora tentang “kesadaran minoritas” dan rasa “ketidakberdayaan pada nasib”, yang membuat saya semakin serius dalam mempelajari hal-hal baru. Menjelang dewasa adalah usia yang belum cukup matang untuk pergi merantau ke Jakarta.Tapi saya memutuskan pergi ke Jakarta.
Maka sejarah kembali berulang dengan kegetiran yang berbeda. Dalam peradaban yang sama sekali berbeda, aroma kota yang kejam, persaingan yang memerlukan kecerdasan; daya tahan dan kekuatan diri diuji sehabis-habisnya. Sering kali malam-malam saat hening saya memandang langit di kejauhan: membayangkan kampung kelahiran yang bernama Singkawang. Pada zaman ketika nasib mulai membaik di tempat saya memandang kali ini, saya menitikkan air mata. Saya teringat ilalang-ilalang yang menyemak di belakang rumah, burung-burung liar, sungai-sungai yang mengalir, bukit-bukit, hamparan kuil-kuil dan aroma gaharu. Semua tempat, semua tokoh, dan seluruh peristiwa yang berjasa membuat saya kini dapat berdiri dengan tegar, tiba-tiba menjelma menjadi cerita yang penuh cinta. Hingga peristiwa Mei 1998 membakar Jakarta, meluluhlantakkan seluruh harapan, dan membalik sejarah kembali pada titik nol.
Kecemasan, perburuan, pembakaran, pemerkosaan. Saya melihat gelombang ribuan orang memadati bandara untuk menyelamatkan diri: menuju negeri-negeri yang jauh. Saya menjerit lantaran kecintaan pada negeri telah mulai tumbuh semenjak menyadari bahwa saya berbeda. Politik yang membuat saya berbeda, tapi bukankah politik bisa berubah? Buku-buku, sekali lagi telah membuka kotak pandora tentang pemahaman saya terhadap negara, terhadap tanah air, terhadap Singkawang, dan ibu kota tanah air saya, Jakarta. Maka keberanian untuk mati di tempat saya membangun takdir, sepenuh-penuhnya saya sadari. Saya memutuskan untuk tidak pergi mengungsi ke negeri-negeri yang jauh—negeri yang bukan tanah air saya.
Setelah badai politik mereda, saya semakin mencintai puisi. Entah kenapa rasa malu pada ibu guru yang telah membuat saya membenci puisi di bangku SMP, telah membalik kesadaran saya di kemudian hari untuk mencintai puisi. Secara pelan tapi pasti, catatan-catatan kecil saya yang merupakan catatan harian tempat saya menemukan teman bicara, telah berubah menjadi baris-baris puisi.”
Cara Kedua: Kredo Konde
Pada tahun 1970-an, dunia persajakan Indonesia digemparkan oleh penyair Sutardji Calzoum Bachri yang memproklamirkan ‘kredo puisi’. Kredo tersebut bisa dilacak di buku sajak O Amuk Kapak dan buku esai Isyarat.
Kredo, menurut saya, semacam kitab suci penyair. Layaknya sebuah kitab suci, kredo dijadikan anutan, acuan, pedoman, atau tuntunan dalam gerak mencipta sajak. Sajak-sajak yang hendak dilahirkan harus sesuai dengan kredo yang telah diprokamirkan. Kredo inilah yang menimbulkan kontrovesi dari khalayak sastra Indonesia. Sutardji banyak melanggar kode etik bersajak atau bisa dikatakan telah melakukan banyak penyimpangan dalam sajak-sajaknya; penghapusan tanda baca, pemutusan kata, pembalikan kata, penggandengan dua kata atau lebih, penghilangan imbuhan, dan bahkan menabrak rambu-rambu sintaksis dan semantik.
Saya tidak menyebut Sutardji berlindung di bawah naungan ‘licentia poetica’. Tapi Beliau sungguh telah istiqomah dengan jalan yang dipilihnya. Nah, yang perlu disayangkan adalah generasi penyair masa kini; cuma mengekor Sutardji tanpa punya pijakan sendiri yang kukuh dan sekadar menulis sajak yang aneh atau berakrobat kata.
Jika kita cermati sajak-sajak Sutardji, memang Beliau patuh benar dengan kredonya, tapi saya mencium aroma pengkhianatan pada sajak dengan titi mangsa tahun 90-an. Apakah Sutarji sudah tidak percaya dengan kredo kepenyairannya? Apakah Sutardji sudah punya kredo baru yang justru mementahkan sajak-sajak awalnya?
Saya belum mendapatkan jawaban dari dua pertanyaan yang saya ajukan, namun menurut saya, penyair boleh saja mengkhianati kredo yang sudah dilahirkannya selama sang penyair terus berproses menuju kebaruan berbahasa.
Kita kembali ke penyair Hanna Fransisca. Penyair Hanna Fransisca memang tidak secara terang seperti Sutardji dalam memprokalimirkan sebuah kredo bersajak. Tetapi saya menduga bahwa penyair perempuan ini sedang menggelar kredonya. Dugaan saya ini atas dasar:
Pertama: judul buku puisi penyair Hanna Fransisca adalah Konde Penyair Han
Kedua: Hanna Fransisca menulis dalam kata pengantar yang berjudul Konde dan Rambut Saya yang Jelita, “Inilah Konde: metafora tentang benda sederhana yang selama ini mampu membuat rambut keindonesiaan kita yang indah permai ini tidak lepas tergerai dan tercerai-berai. Inilah bunga padma, bunga suci yang tetap indah meski tumbuh di rawa-rawa. Inilah Konde Penyair Han, yang menyanggul sajak dengan bunga padma seperti menyanggul rambut tanah air yang permai.”
Ketiga: Penyair Hanna Fransisca menulis sajak bertajuk ‘Konde’ pada halaman 21.
Saya menyebutnya sebagai ‘Kredo Konde’. Konde? Iya sebuah benda yang biasanya digunakan untuk menyanggul rambut perempuan. Coba kita baca sajak utuh ‘Konde’ dan penggalan sajak ‘Arisan’ di bawah ini:
a. Penyair Han
menyanggul sajak
dengan bunga Padma:
“Tuan, sekepal jantungku berdegup mencarimu,
menggunting urat hasrat dari nafasmu,
dan Tuhanku mengajari menyimak,
mengejar lekuk yang kauasinkan dari hatimu.”
Amin.
(Sajak ‘Konde’ hal. 21)
b. Rambutmu digelung, dengan konde merah
serupa kertas angpao bertuliskan mantra.
(sepenggal sajak ‘Arisan’ hal. 51 tanda miring dari saya)
Ada dua keanehan (dibaca: keunikan atau keistimewaan) dari kedua sajak di atas jika dikaitkan dengan kredo KPH:
- Sajak a tidak memuat kata ‘konde’ padahal jelas berjudul ‘konde’. Justru sebaliknya dengan sajak b; tidak berjudul ‘konde’ tetapi memuat kata ‘konde’
- Sajak a bernada doa yang ditandai kata ‘amin’ sedangkan sajak-sajak yang berjudul doa tidak mengusung kata ‘amin’. Bisa ditemui di sajak ‘Doa Sajak Vihara’ hal. 121, sajak ‘Doa Sebelum Terbit Matahari’ hal. 122, sajak ‘Doa Sebelum Malam’ hal. 123, dan sajak ‘Doa Pagi Tepian Lubuk’ hal. 124.
Dua keanehan di atas tidak mempengaruhi bangunan sajak secara keseluruhan. Secara teks, memang bertolak belakang, tetapi secara kontekstual atau ruh justru mendarahdagingkan.
Penyair Hanna Fransisca menyatakan bahwa konde adalah sebuah metafora. Lalu apa sebenarnya metafora itu? Albertine Minderop mengutip pendapat Reaske (2010):
Metaphor: the figure of speech which compares one thing to another directly. Usually a metaphor is created through the use of some from of the verb “to be” For instance, if we say, “life is hungry animal,” hungry animal has become a metaphor for a life. If a poet writes, “my love is a bird, flying in all directions,” the bird has become a metaphor of the poet’s love (Reaske, 1966:37).
Teks inggris di atas sudah jelas meski tidak diterjemahkan. Reaske mendefinisikan metafora sebagai gaya bahasa yang membandingkan satu benda dengan benda lainnya secara langsung yang dalam bahasa Inggris menggunakan to be. Misalnya kita mengatakan, “kehidupan ini binatang lapar” binatang lapar merupakan metafora kehidupan, yakni kehidupan yang serakah dan ganas. Atau seorang penyair yang berujar, “Cintaku burung terbang yang mengembara ke segala arah” burung terbang merupakan metafora dari cinta sang penyair yang bebas ke mana/siapa saja.
Metafora, kata Monroe, adalah “puisi dalam miniatur”. Metafora menghubungkan makna harfiah dengan makna figuratif dalam karya sastra. Dalam hal ini, karya sastra merupakan karya wacana yang menyatukan makna eksplisit dan implisit. Dalam tradisi positivisme logis, perbedaan antara makna eksplisit dan implisit diperlakukan dalam perbedaan antara bahasa kognitif dan emotif, yang kemudian dialihkan menjadi perbedaan menjadi vokabuler denotasi dan konotasi. Denotasi dianggap sebagai makna kognitif yang merupakan tatanan semantik, sedangkan konotasi adalah ekstra-semantik.
Dalam retorika tradisional, metafora digolongkan sebagai majas yang mengelompokkan variasi-variasi dalam makna ke dalam pengalaman kata-kata, atau lebih tepatnya proses denominasi. Aristoteles, dalam Poetic’s-nya, menjelaskan bahwa metafora adalah “penerapan kepada suatu benda atau nama yang termasuk sesuatu yang lain, interferensi yang terjadi dari jenis ke jenis spesies, dari spesies ke jenis, dari spesies ke spesies, atau secara proporsional”. Oleh karena itu, metafora memiliki ide lebih banyak dari kata untuk mengungkapkan kaya itu, metafora akan meregangkan makna kata-kata yang dimiliki melampaui pemakaian biasanya (Ricoeur, 1976: 45).
Supaya lebih jelas, kita nikmati sajak Charil Anwar berikut ini:
Kalau sampai waktuku
‘Ku mau tak seorang kan merayu
Tidak juga kau
Tak perlu sedu sedan itu
Aku ini binatang jalang
Dari kumpulannya terbuang
Biar peluru menembus kulitku
Aku tetap meradang menerjang
Luka dan bisa kubawa berlari
Berlari
Hingga hilang pedih peri
Dan aku akan lebih tidak perduli
Aku mau hidup seribu tahun lagi
(Sajak “Aku”, Chairil Anwar, “Aku Ini Binatang Jalang”, Gramedia Pustaka Utama:
Jakarta, cetakan kedua puluh satu, juli 2009 garis miring dari saya)
Aku ini binatang jalang, ujar Chairil Anwar. Binatang jalang adalah metafora dari kehidupan si aku lirik yang bebas dan ingin merdeka dari segalanya. Metafora binatang jalang dimanfaatkan penyair untuk menguatkan atau mempertegas tekad atau kehendak yang ingin disampaikan kepada pembaca.
Lalu apa metafora dari konde dalam sajak penyair Hanna Fransisca? Kita tak perlu pusing, karena sang penyair menyatakan sendiri dalam Konde dan Rambut Saya yang Jelita, “Inilah Konde: metafora tentang benda sederhana yang selama ini mampu membuat rambut keindonesiaan kita yang indah permai ini tidak lepas tergerai dan tercerai-berai. Inilah bunga padma, bunga suci yang tetap indah meski tumbuh di rawa-rawa. Inilah Konde Penyair Han, yang menyanggul sajak dengan bunga padma seperti menyanggul rambut tanah air yang permai.”
Cara Ketiga: Menerawang Singkawang
Penyair Hanna Fransisca (Zhu Yong Xia) lahir 30 Mei 1979, di Singkawang, Kalimantan Barat. Saya belum tahu banyak tentang biografi penyair kita ini selain informasi dari buku puisi KPH. Di situ, penyair tidak begitu jelas melakukan periodeisasi hidupnya, bisa dimaklumi karena ini bukan buku biografi.
Penyair kita ini menjalani masa kanak dan remaja di tempat kelahirannya, Singkawang. Dan menjelang dewasa, sang penyair merantau ke Jakarta. Di perantaun inilah sang penyair menuliskan sajak-sajak yang kemudian diterbitkan KataKita, Depok.
“…Hingga kemudian saya berhenti sekolah (saya hanya lulus sekolah formal setingkat SMP), dan kemudian menjadi pelayan toko.
(Konde dan Rambut Saya yang Jelita, hal. 14)
“….Menjelang dewasa adalah usia yang belum cukup matang untuk pergi merantau ke Jakarta.Tapi saya memutuskan pergi ke Jakarta.”
(Konde dan Rambut Saya yang Jelita, hal. 15)
Dari 67 sajak dalam KPH, hampir 99 % ditulis di Jakarta. Yang menarik adalah sang penyair juga menulis beberapa sajak yang beraroma kota kelahirannya, Singkawang. Memang, jurus seperti ini sudah biasa dilakukan banyak penyair. Tapi yang istimewa dari Hanna Fransisca adalah dia bisa mengambil jarak dengan objek sajak. Berbeda dengan penyair D. Zawawi Imron dan Abdul Hadi W.M, misalnya.
Kita tahu, D. Zawawi Imron terkenal sebagai duta sajak Madura yang dijuluki ‘celurit emas’. Sepuluh (?) buku puisi tunggal D. Zawawi Imron selalu basah dengan desah Madura. Dari sepuluh (?) itu, yang paling kental Madura-nya adalah Semerbak Mayang (1977), Madura, Akulah Lautmu (1978), dan Bantalku Ombak Selimutku Angin (1996).
Kita kembali ke penyair Hanna Fransisca. Saya mendapatkan 6 sajak yang secara tersurat maupun tersirat berbicara tentang Singkawang, yaitu:
1. Sajak ‘Amoi’ hal. 26
2. Sajak ‘Taiwan di Kolam Mataku’ hal. 35
3. Sajak ‘Kepada Adik’ hal. 40
4. Sajak ‘Singkawang, 1’ hal. 68
5. Sajak ‘Singkawang, 2’ hal. 69
6. Sajak ‘Kapuas’ hal. 79
Saya tampilkan sajak utuh ‘Singkawang, 2’ dan sajak ‘Madura, Akulah Darahmu’ karya D. Zawawi Imron sebagai pembanding:
a. Gemericik sungai, lumut menjulur, ikan-ikan yang subur!
Tepi kolam menepi, bebiji sawi mengalir mimpi.
Kau jala pesona, hijau memanjang,
memadat dalam ranum pepaya.
Harum keringat, sunyi matahari, hijau dingin.
Seekor sriti hinggap di tepi langit.
Rindu tanah, rindu air, rindu kesuburan.
(Sajak ”Singkawang, 2′, Hanna Fransisca, hal. 69, ditulis di Jakarta, September
2009)
b. Di atasmu, bongkahan batu yang bisu
Tidur merangkum nyala dan tumbuh berbunga doa
Biar berguling di atas duri hati tak kan luka
Meski mengeram di dalam nyeri cinta tak kan layu
Dan aku
Anak sulung yang sekaligus anak bungsumu
Kini kembali ke dalam rahimmu, dan tahulah
Bahwa aku sapi kerapan
Yang lahir dari senyum dan airmatamu
Seusap debu hinggaplah, setetes embun hinggaplah,
Sebasah madu hinggaplah
Menanggung biru langit moyangku, menanggung karat
Emas semesta, menanggung parau sekarat tujuh benua
Di sini
Perkenankan aku berseru:
– madura, engkaulah tangisku
bila musim labuh hujan tak turun
kubasuhi kau dengan denyutku
bila dadamu kerontang
kubajak kau dengan tanduk logamku
di atas bukit garam
kunyalakan otakku
lantaran aku adalah sapi kerapan
yang menetas dari senyum dan airmatamu
aku lari mengejar ombak, aku terbang memeluk bulan
dan memetik bintang-gemintang
di ranting-ranting roh nenekmoyangku
di ubun langit kuucapkan sumpah:
– madura, akulah darahmu.
(Sajak “Madura, Akulah Darahmu” dalam ‘Madura, Akulah Lautmu’, D. Zawawi
Imron, 1996: 98-99)
Dari kedua sajak penyair yang berbeda di atas, saya menghasilkan beberapa kesimpulan:
- Sajak ‘Singkawang, 2’ karya Hanna Fransisca lahir dari rindu dan kenangan. Sedangkan sajak ‘Madura, Akulah Darahmu’ karya D. Zawawi Imron lahir dari sebuah pengakuan dan kesaksian yang dalam bahasa agama (Islam) disebut sebagai ‘syahadat’.
- Sajak ‘Singkawang, 2’ karya Hanna Fransisca lebih dekat dengan puisi lama semacam pantun. Sedangkan sajak ‘Madura, Akulah Darahmu’ karya D. Zawawi Imron lebih akrab dengan puisi modern yang memberikan keluasan berekspresi.
- Sajak ‘Singkawang, 2’ karya Hanna Fransisca sederhana dalam pengungkapan dan tidak terlalu hiperbolis dalam memuja sesuatu. Sedangkan sajak ‘Madura, Akulah Darahmu’ karya D. Zawawi Imron terlalu hiperbolis – jika tidak boleh menggangap berlebihan- yang menyebabkan sajak tergelincir pada pengkultusan sesuatu.
Mari kita telaah lebih lanjut dengan konsentrasi nomor 3:
1. a. Gemericik sungai, lumut menjulur, ikan-ikan yang subur!
Tepi kolam menepi, bebiji sawi mengalir mimpi.
2. a. Dan aku
Anak sulung yang sekaligus anak bungsumu
Kini kembali ke dalam rahimmu, dan tahulah
Bahwa aku sapi kerapan
Yang lahir dari senyum dan airmatamu
1. b. Kau jala pesona, hijau memanjang,
memadat dalam ranum pepaya.
Harum keringat, sunyi matahari, hijau dingin.
2. b. Di sini
Perkenankan aku berseru:
– madura, engkaulah tangisku
3. a. Seekor sriti hinggap di tepi langit.
Rindu tanah, rindu air, rindu kesuburan.
3. b. bila musim labuh hujan tak turun
kubasuhi kau dengan denyutku
bila dadamu kerontang
kubajak kau dengan tanduk logamku
di atas bukit garam
kunyalakan otakku
lantaran aku adalah sapi kerapan
yang menetas dari senyum dan airmatamu
Keterangan: 1, 2, 3 a adalah bait-bait milik sajak Hanna Fransisca dan 1, 2,3 b milik sajak D. Zawawi Imron
Kelebihan penyair D. Zawawi Imron dalam sajak ‘Madura, Akulah Darahmu’ adalah kepiawaiannya menyelundupkan ‘benda-benda’ yang kemudian dipekerjakan sebagai personifikasi dan dihiperbolakan. Teknik ini memang menarik, tetapi jika berlebihan, justru akan mengurangi nilai atau keagungan yang diapresiasi. Nah, inilah yang hendak dihindari oleh penyair Hanna Fransisca. Dia menyajakkan Singkawang tanpa pemujaan yang berlebihan, misalnya dia cuma menulis, “Kau jala pesona, hijau memanjang/ memadat dalam ranum papaya/ Harum keringat, sunyi matahari, hijau dingin.// dan dia bisa mengambil jarak dengan objek sajak; seolah-seolah Hanna Fransisca adalah orang ‘di luar’ Singkawang yang mengagumi Singkawang, sehingga apa adanya dalam memberi penilaian. Barangkali pengakuan Hanna Fransisisca ini yang menyebabkannya bisa mengambil jarak dengan objek sajak:
“Maka sejarah kembali berulang dengan kegetiran yang berbeda. Dalam peradaban yang sama sekali berbeda, aroma kota yang kejam, persaingan yang memerlukan kecerdasan; daya tahan dan kekuatan diri diuji sehabis-habisnya. Sering kali malam-malam saat hening saya memandang langit di kejauhan: membayangkan kampung kelahiran yang bernama Singkawang. Pada zaman ketika nasib mulai membaik di tempat saya memandang kali ini, saya menitikkan air mata. Saya teringat ilalang-ilalang yang menyemak di belakang rumah, burung-burung liar, sungai-sungai yang mengalir, bukit-bukit, hamparan kuil-kuil dan aroma gaharu. Semua tempat, semua tokoh, dan seluruh peristiwa yang berjasa membuat saya kini dapat berdiri dengan tegar, tiba-tiba menjelma menjadi cerita yang penuh cinta.”
(Konde dan Rambut Saya yang Jelita, hal. 15-16 garis miring dari saya)
Menurut pengakuan Hanna Fransisca, sajak ‘Singkawang, 2’ ditulis di Jakarta, September 2009, ini berarti Hanna sedang menghadirkan Singkawang ke dalam sajaknya dan bukan sajak yang menghadiri Singkawang. Gerak ‘menghadirkan’ dan gerak ‘menghadiri’ jelas menghasilkan sajak yang berbeda. Dalam gerak ‘menghadirkan’, imaji lebih bermain ketimbang menimbang-nimbang objek pada gerak ‘menghadiri’, misalnya pada sajak-sajak D. Zawawi Imron.
Sebenarnya ada yang lebih membuat saya tertarik dari sajak ‘Singkawang, 2’ adalah sebagai berikut:
- ikan-ikan yang subur!
- memadat dalam ranum pepaya.
- hijau dingin
Aduhai, alangkah rekah kata-kata itu! dari sisi sintaksis dan semantik, bait-bait di atas bisa dipertanggungjawabkan.
Cara Keempat: Negeri yang Ngeri
(1) Hingga peristiwa Mei 1998 membakar Jakarta, meluluhlantakkan seluruh harapan, dan membalik sejarah kembali pada titik nol.
(2) Kecemasan, perburuan, pembakaran, pemerkosaan. Saya melihat gelombang ribuan orang memadati bandara untuk menyelamatkan diri: menuju negeri-negeri yang jauh. Saya menjerit lantaran kecintaan pada negeri telah mulai tumbuh semenjak menyadari bahwa saya berbeda. Politik yang membuat saya berbeda, tapi bukankah politik bisa berubah? Buku-buku, sekali lagi telah membuka kotak pandora tentang pemahaman saya terhadap negara, terhadap tanah air, terhadap Singkawang, dan ibu kota tanah air saya, Jakarta. Maka keberanian untuk mati di tempat saya membangun takdir, sepenuh-penuhnya saya sadari. Saya memutuskan untuk tidak pergi mengungsi ke negeri-negeri yang jauh—negeri yang bukan tanah air saya.
Dua petikan di atas sengaja saya dahulukan. Betapa kondisi dan situasi yang melingkupi Hanna amat miris dan mengiris. Itulah sebab yang melahirkan sajak-sajak berikut ini:
- Sajak ‘Di Sudut Bibirmu Ada Sebutir Nasi’ hal. 22
- Sajak ‘Air Mata Tanah Air’ hal. 27
- Sajak ‘Lilin Negeri, 1’ hal. 32
- Sajak ‘Lilin Negeri, 2’ hal. 33
- Sajak ‘Sang Naga’ hal. 34
- Sajak ‘Puisi Mei’ hal. 42
- Sajak ‘Nyanyi Tanah Negeri’ hal. 43
- Sajak ‘Rapat’ hal. 49
- Sajak ‘Kerbau’ hal. 57
Saya akan mengutip beberapa bait dari sajak ‘Di Sudut Bibirmu Ada Sebutir Nasi’ dan sajak ‘Puisi Mei’:
Setelah tak lulus SMP Negeri, setelah guru
tulen pribumi dengan pasti mengatainya:
“Di sudut bibirmu ada sebutir nasi.
Bukan tempatmu di sini.”
……………………….
“Engkau hanyalah tamu
tanah dan air, menunggu di beranda
sampai mati.”
………………………..
“Kelahiranmu di bumi pertiwi,
membikin wajah negeri cantik sekali.”
………………………..
Di mulut ibu guru yang menyebut namamu noni,
di kepala anak-anak yang mengaku diri pribumi,
di benak mereka yang selalu menunggu waktu
untuk membakar bulu kemaluanmu.
(Cuplikan-cuplikan dari sajak ‘Di Sudut Bibirmu Ada Sebutir Nasi’ hal. 22-25)
Pernahkah kau saksikan tarian jujur
yang memaku matamu hingga ke ujung kubur?
Kulit mayat daging bebas kau lumat
Puing-puing tegak, di bawah tiang bendera Negara,
membawa kau, yang kini kusebut kalian,
pada gairah syahwat.
Debu gemuruh
nafsu gemuruh:
kausebut aku dungu
Inilah Negeri Mei, Amoi!
tarian naga meliuk merah sepanjang kota
Kau kibarkan tanda kutang tepat di bawah warna
bendera,
merah dan putih.
Seperti darah. Seperti kulit.
“Mari membakar sate, dari pekik anak dara yang
Belum lulus esde.”
Lalu kalian menyambutnya dengan sederhana,
dengan menjarah lorong-lorong kota
sambil menyanyikan bersama: Padamu Negeri.
(Sajak utuh ‘Puisi Mei’ hal. 42)
Tanpa tafsir yang rumit, sebenarnya kedua sajak di atas sudah berbicara sendiri tentang apa yang hendak diketengahkan sang penyair. Dari kedua sajak di atas, saya peroleh beberapa ironi dan tragedi:
Pertama: kebencian pribumi terhadap etnis Tionghoa atau China
Kedua: tumbuh subur rasisme
Ketiga: pelecehan fisik maupun psikis yang lebih dikenal dengan ‘Tragedi Mei’ (13-14 Mei 1998)
Keempat: kegagalan pemerintah melindungi rakyat
Saya sendiri anti pengkotakan-pengkotakan dalam bentuk apapun, misalnya penyebutan ‘pribumi’ dan ‘peranakan atau keturunan’. Dan yang aneh dan ajaib, ternyata pemerintah adalah biang kerok terhadap kejadian-kejadian mengerikan itu. Pemerintah pada masa Soeharto (orde baru/orba) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) dan Intruksin Presiden (Inpres) yang isinya antara lain berupa pelarangan sekolah dan penerbitan buku, Koran, ataupun majalah berbahasa China:
- Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/krp/12/1968 mengenai penggantian nama,
- Inpres No. 14/1967 yang mengatur agama, kepercayaan, dan adat istiadat keturunan China,
- Keppres No. 240/1967 mengenai kebijakan pokok menyangkut WNI keturunan asing dan
- Inpres Kabinet No. 37/U/IN/6/1967 tentang kebijaksanaan pokok penyelesaian masalah China.
Sungguh saya meneteskan air mata ketika penyair Hanna Fransisca membisiki telinga saya, “Di sudut bibirmu ada sebutir nasi/ Bukan tempatmu di sini.// dan Engkau hanyalah tamu/ tanah dan air/ menunggu di beranda/ sampai mati.// sungguh bagaimana perasaan saya jika berada di posisi penyair Hanna Fransisca? Seorang anak yang tidak diakui ibu pertiwi. Seorang anak manusia yang hanya dianggap sebagai ‘tamu’ yang kemudian diusir ‘tuan rumah’ dan entah mengembara ke mana. Ah, cukup, saya tidak mau membahas lagi tentang kepedihan ini!
Seorang Hero atau Pahlawan akan hadir dalam masa vacum of power. Di mana sang Maha yang disimbolikkan dengan Dewa atau Tuhan tidak hadir di air mata yang mengalir. Ketika malapeteka menimpa, dirundung mendung ketakberdayaan, dikepung ombak badai dari segala arah penjuru, manusia membutuhkan sesuatu atau seseorang yang meneduhkan dan membawanya ke jalan penyelamatan. Dan sang Hero adalah juru selamat bukan juri pertandingan. Dia adalah Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Pada tanggal 18 Januari 2000, Presiden KH. DR. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6/2000 yang isinya mencabut Inpres No. 14/1967. Kebijakan Gusdur itu melahirkan kebebasan etnis Tionghoa dalam menjalankan ritual keagamaan, adat istiadat, serta memperbolehkan pengekspresian terhadap kebudayaannya di Indonesia. Presiden Abdurrahman Wahid telah mengambil keputusan bersejarah dan monumental. Maka tak heran bila Gus Dur dianugerahi gelar Bapak Tionghoa.
Penyair Hanna Fransisca sebagai anak sah ibu pertiwi yang baik menciptakan tiga sajak yang khusus diberikan kepada Abdurrahman Wahid sebagai tanda jasa atau ungkapan rasa terima kasih, yaitu:
- Sajak ‘Air Mata Tanah Air’ hal. 27
- Sajak ‘Lilin Negeri, 2’ hal. 33
- Sajak ‘Sang Naga’ hal. 34
Saya petik bait terakhir sajak ‘Sang Naga’ pada halaman 34. Penyair Hanna amat cermat memanfaatkan tokoh ‘naga’ sebagai simbol dari si aku lirik.
“Engkau.
Engkau adalah putriku,
naga yang ditolak separuh badan,
untuk dimakan separuh yang lain.
tapi kini datanglah! Kau aman
di pelukan hatiku.”
Cara Kelima: Marginalisasi Perempuan dan Pemberontakan dalam Puisi
Entah sejak kapan sejarah marginalisasi perempuan bermula. Ada yang mengatakan bahwa Tuhanlah yang merestui ini yang berpijak pada kitab suci. Akhirnya ramai-ramai para ahli agama mendekontruksi dan merekontruksi tafsir keagaaman. Misalnya penelusuran kembali siapa yang bersalah atas ditendangnya Adam dan Hawa ke alam dunia. Yang kemudian dikenal sebagai ‘dosa asal’.
Terlepas dari polemik dosa asal di atas, saya bisa mengerucutkan sebab marginalisasi perempuan:
Pertama: Budaya patriaki, di mana laki-lakilah yang paling hero dari perempuan dalam segala bidang dan perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap.
Kedua: Kondisi ekonomi, di mana perempuan harus terus berjuang melawan ketidakadilan-ketidakadilan yang lebih dilatarbelakangi oleh kebijakan-kebijakan yang tidak memihak. Dari beberapa referensi, saya peroleh bahwa ‘amoi’ adalah seseorang yang tidak punya nilai tawar dalam masyarakat kapitalistik. Dia selalu jadi tumbal nasib yang salib. Nasibnya akan berubah jika dinikahi lelaki-lelaki asal Taiwan atau Hongkong yang baik hati, jika tidak, nasibnya lebih mengerikan.
Saya dapati beberapa sajak yang berbicara tentang tema yang sedang saya bicarakan:
- Sajak ‘Amoi’ hal. 26
- Sajak ‘Perempuan Tanpa Bulu’ hal. 64
- Sajak ‘Bulu Kaki Mata Sipit’ hal. 66
- Sajak ‘Gerhana’ hal. 81
- Sajak ‘Puisi Kupu-Kupu’ hal. 86
- Sajak ‘Puisi Piring Kaleng’ hal. 88
- Sajak ‘Puisi Kacang Hijau’ hal. 90
- Sajak ‘Puisi Roda Pedati’ hal. 92
Mari kita resapi beberapa petikan sajak berikut ini:
a. bunga yang koyak tenggelam, beribu perawan,
dipaksa pergi menyongsong angin
(bait terakhir sajak ‘Amoi’ hal. 26)
b. Di Pecinan hanya amoi yang mesti telanjang,
sebab bulu bagi suami adalah hitungan rezeki
yang harus pasti.
…………….
“Dara manis, jangan menangis. Lelaki tak pernah sedih
saat menceraimu di pagi sedih.”
………………
Hanya di Pecinan, amoi malang mesti telanjang.
Menjadi pengantin sedih di pagi sedih,
atau mempelai penuh berkah, yang kelak berubah
menjadi tuah
(Petikan-petikan sajak ‘Perempuan Tanpa Bulu’ hal. 64-65)
c. Kausesali ibu yang melahirkan perempuanmu,
kaucaci leluhur yang menjadikan kau pengantin mati
hingga pagi hari.
………………..
“Sungguh layak bagi kau, jika pengantinmu
menjual diri di jalan raya.”
(Dua cuplikan sajak ‘Bulu Kaki Mata Sipit’ hal. 66-7)
d. Tapi sebilah tombak selalu telah membelah sayapku
Jalan yang kini bercabang kian menjulang
Aku melayang gentayangan menuntaskan angan yang makin memanjang
(bait terakhir sajak ‘Puisi Roda Pedati’ hal. 93)
Tapi si aku lirik tidak begitu saja menerima pelecehan dan penindasan, ia berusaha melawan atau memberontak walau dengan suara parau dan tenaga yang ringkih:
e. Mari kuajak kau meneguk racun
dengan secangkir kopi pahit,
dan kuceritakan padamu tentang bulu kaki
yang bikin lelakimu mati.
(bait pembuka sajak ‘Bulu Kaki Mata Sipit’ hal. 66)
f. Maka doa kalian, para petualang,
jangan kira jalan lempang selalu menuntunmu
pada asal dosa, dan menebusnya dengan nikmat
yang membawa terbang kupu-kupu
dari tebing yang berkilau cahaya, menuju lembah air
tempat engkau memandikan perempuanmu
dengan harum apel yang kaukira
jatuh dari surga.
(sebait sajak ‘Puisi Kupu-Kupu’ hal. 86)
g. “Bertahanlah Moi,
jangan takut rumput menutup jalan
sebab harum bunga akan bicara.”
……………
“Aku ingin memintal cahaya
menjadi lingkaran kemilau tanpa bahaya.”
(dua petikan sajak ‘Puisi Piring Kaleng’ hal. 88)
Cara Keenam: Apa Guna Sajak?
Apa yang berharga dari puisiku, tanya penyair Wiji Thukul atau tanya Subagio Sastrowardoyo, Apakah arti sajak ini. Bagaimana menurut Penyair Hanna Fransisca? Apakah dia juga punya pertanyaan sama dengan penyair Wiji Thukul dan Subagio Sastrowardoyo? Apa yang melatarbelakangi Hanna Fransisca menulis sajak-sajak yang terhimpun dalam Konde Penyair Han? Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dijawab oleh sang penyair melalui kata pengantar yang berjudul ‘Konde dan Rambut Saya yang Jelita’ halaman 11-19. Saya kutipkan beberapa kalimat di bawah ini (tanda miring dari saya):
(1) Saya kira pada waktu-waktu yang paling buruk itulah saya menulis puisi. Saya kira bukan puisi, tapi hanya semacam puisi. Saya menulis catatan keluh-kesah dengan diam-diam, menyembunyikannya dengan diam-diam dalam buku tulis, dan tak seorangpun boleh tahu.
(2) Saya adalah anak perempuan pemalu yang tak pernah memiliki keberanian untuk berbicara, tak pernah memiliki keberanian untuk memulai berteman, atau untuk bertanya soal apa saja kepada siapa saja. Maka saat menulis saya memiliki tempat paling nyaman untuk berbicara.
(3) Saya terus menulis yang bukan puisi, di dalam buku yang selalu diam tapi sesungguhnya mengajak saya bicara. Saya selalu katakan bukan puisi, karena sejak hari memalukan itu, saya membenci puisi. Tentu saya tetap suka membaca cerita, karena buku-buku cerita sudah jelas bukan puisi.
(4) maka di sela-sela tumpahan waktu untuk kerja, saya selalu membutuhkan buku-buku. Buku-buku itulah, yang kelak secara ajaib telah membuka kotak pandora tentang “kesadaran minoritas” dan rasa “ketidakberdayaan pada nasib”, yang membuat saya semakin serius dalam mempelajari hal-hal baru.
(5) Sering kali malam-malam saat hening saya memandang langit di kejauhan: membayangkan kampung kelahiran yang bernama Singkawang.
(6) Setelah badai politik mereda, saya semakin mencintai puisi. Entah kenapa rasa malu pada ibu guru yang telah membuat saya membenci puisi di bangku SMP, telah membalik kesadaran saya di kemudian hari untuk mencintai puisi. Secara pelan tapi pasti, catatan-catatan kecil saya yang merupakan catatan harian tempat saya menemukan teman bicara, telah berubah menjadi baris-baris puisi.”
Pada tulisan bagian pertama sudah saya singgung soal luka sebagai bahan bakar sajak; baik luka diri pengarang maupun luka orang-orang yang berada di sekitar pengarang. Jika meminjam bahasa penyair Triyanto Triwikromo dalam kata pengantarnya pada buku puisi Kembang Setaman, ia mengatakan bahwa peradaban yang luka sebagai pusat penciptaan puisi.
Apa yang dilakukan Hanna Fransisca adalah sesuai dengan pesan penyair Inggris, Jhon Keats, puisi adalah satu-satunya yang mampu merangkul keasingan. Kita tahu bahwa masa kanak Hanna Fransisca diliputi kesendirian dan keterluntaan nasib. Bagi saya, itulah keasingan yang dimaksud Jhon Keats. Hanna Fransisca mencoba mengikis – atau justru ingin menikmati – keasingan itu dengan memandang ilalang-ilalang yang bergoyang di belakang rumahnya. Kemudian berlanjut dengan mencintai buku-buku bacaan dan bergerak untuk menuliskan gairah dan gerahnya pada kehidupan. Kau kemudian hanya mengenal satu bunyi: puisi, tulis Hanna Fransisca dalam sajak ‘Puisi Piring Kaleng’ halaman 89.
Penyair Subagio Sastrowardoyo pernah menulis puisi berjudul ‘Sajak’ yang berkenaan dengan peran atau guna sajak bagi kehidupan.
“Ah, sajak ini,
mengingatkan aku kepada langit dan mega.
Sajak ini mengingatkanku kepada kisah dan keabadian.
Sajak ini melupakanku aku kepada pisau dan tali.
Sajak ini melupakan kepada bunuh diri”
Penyair Subagio Sastrowardoyo sebelumnya bertanya dengan kalimat yang menggugat sebanyak tiga kali: Apakah arti sajak ini. Ini berarti setiap penyair punya alasan dan jawaban sendiri dan berbeda kenapa dirinya menulis sajak. Di sini, saya menolak anggapan bahwa menjadi penyair adalah sebuah kutukan. Kutukan siapa?
Lain lagi dengan penyair Acep Zamzam Noor, menulis sajak adalah melayani kerinduan yang menyerang. Seperti yang ditulis dalam sajak ‘Mengapa Selalu Kutulis Sajak’ pada buku puisi Tamparlah Mukaku.
Mengapa selalu kutulis sajak
Apabila kerinduan tiba-tiba menyerbuku
Mengapa harus sajak, kekasihku, mengapa harus ia
Yang mampu kupersembahkan kepadamu.
Epilog
Karena segalanya harus ada akhir, maka perkenankan saya mohon maaf kepada penyair Hanna Fransisca dan Pembaca atas keterbasan saya dalam mengulas buku KPH. Terima kasih dan salam hormat dari saya.
“Setiap hendak kutangkap
Ia lolos dari dekap
Tak mampu menampung rasa
(Sajak ‘Yang Tak Peduli’, Subagio Sastrowardoyo)
Malang, 22 April 2011
*) Syaiful Alim, Penulis novel Kidung Cinta Pohon Kurma