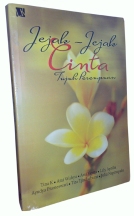Oleh Ade Anita
Pagi-pagi jika menulis sesuatu yang rada-rada “dewasa” nggak apa-apa ya… hitung-hitung buat menghangatkan pagi.
Dulu, waktu saya masih kuliah (baru tahun kedua kalau nggak salah), saya punya teman orang bule. Dengan bermodalkan wajah saya yang kata orang innocent (tanpa dosa dan polos), saya bertanya pada teman bule saya itu, yang kebetulan seorang pria yang usianya lebih tua dari saya beberapa tahun. Ketika itu, kami sedang menunggu kereta api yang datang terlambat seperti biasa di sebuah stasiun kereta api menuju Depok.
“Kamu… sudah pernah melakukan hubungan seks belum?”
(kalau dipikir sekarang, gila banget ya saya bertanya hal seperti ini padanya, Kurang kerjaan banget). Teman bule saya itu kaget, dan dengan alis mata yang saling bertautan dia menatap saya bingung. Saya hanya cengar-cengir dan mengatakan:
“Just want to know.”
“Kamu sendiri? Sudah pernah belum?”
Saya menggeleng, masih dengan cengar-cengir yang culun abis.
“Di Indonesia, hal-hal seperti itu tidak boleh dilakukan sebelum terjadinya sebuah pernikahan.”
Teman bule saya mengangguk-angguk.
“Tapi, itu kan pilihan. Saya bertemu dengan beberapa orang dan mereka ternyata tidak seperti yang kamu katakan tadi, mereka sudah melakukannya meski mereka belum menikah.”
“Well, kebetulan saya termasuk orang yang memilih untuk tidak melakukannya sebelum terjadinya sebuah pernikahan.”
“And Are you happy with that?”
Saya mengangguk. Lalu kami berbincang panjang tentang perkara seks ini seperti halnya sedang membicarakan masalah politik saja, atau seperti membicarakan tentang gosip para selebritis. Saya memang senang ngobrol dari dulu, tapi selalu berusaha untuk membuat obrolan senetral mungkin. Tidak senang menggiring obrolan ke arah lain yang berpotensi yang bukan-bukan.
“Jadi, usia berapa kamu melakukan hubungan seks pertama kali? What is your virgin story?”
Teman bule saya mengangkat telunjuknya ke depan hidung saya.
“Ya, maksud saya kamu. Usia berapa?”
Saya kembali bertanya. Teman bule saya tersenyum.
“Iya, saya bukan sedang mengangkat telunjuk. Tapi saya ingin memberitahumu, saya melakukannya ketika saya berusia sebelas tahun.”
WHAT!!!!
Gila dasar bule ini. Tapi, ternyata pengetahuan baru ini berguna bagi saya untuk memahami sebuah pernikahan dini yang gonjang-ganjingnya sempat ramai beberapa tahun yang lalu di Indonesia.
Kebetulan, saya mengasuk rubrik Uneg-uneg di kafemuslimah.com. Sebuah surat curhat datang ke email saya bertanya tentang pernikahan dini tersebut. Sebut saja Mr X yang ingin menikahkan anaknya yang baru berusia 13 tahun dengan seorang yang menurutnya cocok untuk jadi pendamping hidup anaknya. Tapi, dia mendapat kesulitan secara administrasi karena terbentur dengan undang-undang perkawinan yang mengharuskan calon pengantin wanita berusia 16 tahun minimal. Dia merasa terzolimi dengan keberadaan undang-undang perkawinan tersebut.
Akhirnya, saya memaparkan kepada Mr X itu, bahwa memang dalam Islam, hasil kesepakatan ulama mengatakan bahwa seorang perempuan yang siap menikah itu adalah ketika si perempuan sudah siap untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya. Dan itu artinya, usianya bisa amat dini, lebih dini dari usia yang digaris-bawahin oleh UNdang-undang perkawinan kita yang 16 tahun itu (masih ingat kan, cerita tentang teman bule saya yang melakukan hubungan seksual dengan teman sekolahnya di usia 11 tahun di atas?).
Tapi, perkawinan itu tidak melulu berisi tentang hubungan seksual saja. Ada rentetan kejadian berikutnya, seperti mengandung, melahirkan, mengasuh anak (dan ketiga kejadian ini tidak boleh terlepas dari bentuk fisik seseorang. Jika tubuh si anak masih terlalu kecil, tentu dia harus kepayahan dalam melakukan ketiga kejadian ini). Kecuali…. jika disepakati untuk merencanakan kesiapan suami istri terlebih dahulu dengan cara menunda memiliki momongan. Dengan demikian, si anak bisa terus melanjutkan sekolahnya, karena tidak bisa dipungkirin bahwa pendidikan itu amat berguna bagi pembekalan seseorang dalam menapak kehidupan rumah tangganya. Bukankah tidak selamanya keberuntungan ada di pihak kita? Kita harus siap jika terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki dan ilmu adalah bekal yang tidak akan kadaluarsa. Ada banyak keluarga yang terselamatkan oleh kepandaian yang dimiliki oleh sang istri ketika sang suami tersungkur karena cobaan hidup yang beragam. Jadi, pendidikan danketerampilan untuk seorang anak perempuan itu adalah sesuatu yang tidak merugi. Akhirnya, si bapak bisa mengerti.
Fiuh.Case Closed.
Kembali ke teman bule saya itu.
Ternyata, gejolak kebutuhan seks pada beberapa orang itu sudah terasa sejak usia remaja. Adalah sistem nilai sosial budaya kita dan juga tata aturan agama-lah yang paling berjasa membentengi agar para remaja kita tidak sampai melakukan hubungan seks bebas. Untuk itu, tentu peran orang tua amat besar adanya.
Eh… mana dia cerita tentang teman bule saya itu? Kok malah nulis pernyataan resmi? hehehe… kita lupakan si teman bule saya itu. Ceritanya menarik memang, apalagi ketika saya mendengar penuturannya, saya masih benar-benar “hijau dan culun”… Saya ingat dulu, beberapa kali teman bule saya itu harus kesulitan memilih kata-kata untuk bercerita karena tahu saya tidak mengerti apa-apa dan dia berusaha keras untuk menjaga agar saya tidak berubah karena ceritanya. Ketika itu, saya benar-benar berada dalam posisi “saya tahu tapi saya tidak tahu apa-apa”.
Usaha teman bule saya ini amat saya hargai. Kesulitan untuk menjelaskan sesuatu yang “biasa” bagi dirinya pada orang yang “belum biasa” seperti saya bukan sebuah perkara mudah. Saya mengalaminya kemarin. Ketika bersama anak bungsu saya, Hawna (5 tahun 10 bulan), berdua menyaksikan tayangan film remaja bule yang berjudul “10 think I hate about You” di HBO Family.
Saya suka jalinan ceritanya, tapi, amat kepayahan menyensor adegan berciuman yang bertaburan di film tersebut. Mau pindah remote suka kelamaan pindah jadi begitu pindah ke film itu lagi ternyata ketinggalan beberapa scenenya. Nggak pindah ada Hawna di samping saya. Jadi terpaksa deh, tangan saya mampir ke depan matanya, menutup matanya rapat-rapat.
“Eh… Hawna, tutup matanya.”
Hawna cengar-cengir ketawa.
“Sudah ibu, aku sudah nutup mataku. Nanti kalau sudah selesai bilang ya, aku cape nutup mata terus.”
Lalu saya menonton terus sambil makan nasi bungkus padang.
“Oke… sekarang sudah boleh dibuka.”
Lalu adegan demi adegan dalam film itu terus berlangsung hingga tiba-tiba, ada adegan dewasa lagi yang hadir tiba-tiba. Spontan saya berteriak panik karena tangan saya penuh belepotan nasi padang yang padat berkuah.
“Eh… Hawna, tutup hidungnya!.. Eh.. mulutnya… eh.. matanya…!!!”
Hawna sebenarnya sudah langsung memalingkan wajahnya ketika dua kepala dalam film itu sudah mulai berdekatan. Tapi, dia spontan tertawa melihat saya yang panik hingga salah bicara beberapa kali dan dia sudah menutup matanya l jauh sebelum saya berteriak sebenarnya.
Saya ikut tertawa melihat ketololan dan kepanikan saya. Huh! Setelah adegan itu lewat, akhirnya, saya bisa terus makan sambil cukup memerintahkan satu kata saja, “Hawna” dan dia langsung menutup matanya. Hingga akhirnya, dia yang masih menutup matanya tiba-tiba bertanya pada saya,
“Kenapa sih bu, aku nggak boleh lihat orang ciuman?”
Eh… loh? Hmm….
“Darimana kamu tahu kalau itu orang lagi ciuman?”
“Ya tahulah. ya… tahu ajah.”
Huff… tarik napas panjang.
“Karena, adegan itu memang belum waktunya dilihat sama kamu.”
“Kalau sama mbak Arna boleh?”
“Belum boleh juga.”
“Kalau sama mas Ibam?”
Huff lagi….
“Nggak semua hal boleh kamu lihat sayang. Apalagi kalau kamu masih kecil. Kadang, ada hal-hal yang kalau kita lihat malah bikin kita bahaya. Seperti kalau orang lihat rahasia negara misalnya, orang itu bisa dibunuh sama polisi. DOR… DOR….”
Loh, kenapa jadi membicarakan tentang masalah terorisme segala??
“Jadi, kalau aku lihat orang ciuman aku bisa kenapa?”
Oke, Ade, saatnya untuk ngobrak-ngabrik perpustakaan memori di otakmu… pikir…pikir…pikir… ayo, ade pikir…
“Nggak tahu. Tapi, yang pasti kamu akan lebih beruntung kalau kamu melihat itu ketika kamu sudah besar nanti saja. Jangan sekecil ini.”
“Kalau aku sudah sebesar Mbak Arna?”
“Lebih besar lagi.”
“Kayak Mas Ibam?”
Aku melihat ke arah anakku yang berbicara sedari tadi dengan mata tertutup. Aku cium kedua kelopak matanya yang tertutup itu.
“Nanti, saatnya akan datang. Ibu nggak tahu kapan, tapi nggak sekarang yang pasti dan sekarang kamu bisa buka matamu.”
Dia membuka matanya dan melirik film.
“Filmnya sudah habis ya bu?”
“Iya, sudah habis.”
“Ngomong-ngomong, kamu suka nggak nonton film horor?”
“Ihhh… nggak. Aku nggak suka. Serem. Suka ada setannya.”
Saya tertawa melihat reaksi ngeri yang ditampilkan Hawna.
“Tahu nggak, sebenarnya, vampir itu kan kelelawar, tapi sebenarnya, kelelawar itu nggak bahaya sih. Tapi karena kita lihat kelelawar di film horor seram, kita jadi takut sama kelelawar.”
“Iya… aku takut sama kelelawar vampir.”
“Sebenarnya, kelelawar vampr itu nggak ada sayang.”
“Terus.. kenapa di film ada?”
“Ya itulah. Namanya juga film. Dia suka bikin sesuatu yang nggak ada, jadi ada. Atau bikin sesuatu yang nggak boleh dilakuin, jadi boleh dilakuin. Kayak membunuh orang, ngisep darahnya…. brrr…”
Hawna menatapku dengan kedua alis bertaut. Pasti dia bingung.
“Nah, begitu juga dengan orang ciuman. Sebenarnya, buat kita, orang islam dan orang Indonesia, ciuman, pelukan itu cuma boleh dilakukan nanti, kalau sudah nikah. Kayak ibu sama ayah tuh. Tapi, kalau belum nikah nggak boleh. Cuma, karena di film suka lebay, makanya ditampilin orang yang suka ngelakuin itu. Itu sebabnya ibu ngelarang kamu melihatnya.”
“Ooo…. ngerti aku … ngerti.”
(jujur, saya masih bertanya-tanya sebenarnya, dia ngerti beneran nggak sih?)
“Tapi kalau kita lagi liburan ke luar negeri, aku suka lihat orang ciuman?”
“Iya itu tadi… dia orang luar negeri. Mungkin bukan orang Islam kali. Jadi, mending nggak usah dilihat juga.”
Saya meneruskan makan nasi bungkus padang yang tinggal sedikit lagi. Tapi jujur, dalam hati ternyata bertambah lagi pekerjaan rumah saya sebagai seorang ibu.
Lalu, apa hubungannya dengan cerita tentang teman bule saya itu? hehehehe….. ya nggak tahu, namanya juga dia cuma pemanis saja kok di tulisan ini. Saya kebetulan saja inget si bule itu, inget dengan posisi sulitnya ketika saya mengajaknya membicarakan sesuatu dengan posisi saya sebagai seorang yang “tahu tapi sebenarnya tidak tahu apa-apa”. Sulit jeeeh buat njelasinnya.
Begh… sepertinya kena hukum karma. ***