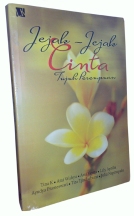Oleh Dwi Klik Santosa
Kula nuwun para sedulur …
Perkenalkan nama saya Tejomantri. Panggilan keren saya Togog. Mohon maaf, jika sesekali saya akan mengeluhkan apa-apa yang akan menjadi keresahan hati saya. Banyak yang tahu, bahwa di dunia pewayangan, saya ini popular dan lebih dikenal secara konotatif karena selalu beriringan dengan tokoh-tokoh sora. Raja jahat, banyak ambisi, dan suka semena-mena, gitulah …. Ya, kalau di zaman sekarang ini, jika harus dilakonkan, mungkin saya masih akan kebagian peran yang tidak jauh-jauh dari lingkup antagonis seperti itu. Mengikuti para-para yang punya kecerdasan, kelihaian, kebagusan, kekuasaan tapi gemar berjudi, manipulasi, menindas, korupsi, suka aleman dan cewekan … hehehe … sepaketlah.
Aduuuuhh … padahal secara genitas, saya ini kan terlahir mulia. Sebagai dewa berjuluk Tejamaya. Yang kalau diartikan bisa berbunyi cahaya langit yang teduh. Coba bayangkan. Lha tapi … ini kan tugas dari Bathara Tunggal, ayah saya. Kewajiban yang harus saya emban, karena lahirku yang serba ajaib dan punya kelebihan yang linuwih.
“Jika pemegang aturan terus dikemudi manusia keblangsak, maka ilmu pengetahuan akan kehilangan makna,” begitu titah beliau.
Dan benar belaka rasanya. Jangankan harkat adat, tradisi dan moral yang adiluhung. Agama yang sakral saja … bisa saja diplintir-plintir, dijadikan kedok-kedok.
Aduuuhhh … Betapa kata-kata ayah itu terus saya pegang dan pahami hingga membumi sebagai amanat yang paling utama.
Tapi, begini lho para sedulur …
Sesungguhnya, sejujurnya saya ingin mengeluh dan curhat. Andai saja sedulur sekalian memahami perasaan saya. Sudah didandani sebagai makhluk buruk begini rupa, ditugaskan pula sampai masa yang tak terbatas. Untuk terus mengiring dan menyaksikan keblangsakan makhluk rakus bernama manusia murtad. Lae … lae …
Tidak bolehkah saya ini sekali-sekali menampilkan kemahiran saya. Kehandalan saya. Kelaziman saya. Yang tentunya selama para sedulur semua terlalu sering mengenal saya sebagai makhluk bego, lupa membaca saya. Bahwa saya ini bisa juga klimis, mahir berjargon. Jago nggombal. Dan berbakat buaya juga … hehehe …
Tapi, … tapi … waduuhhhh … Untuk apa saya harus membajul. Atas nama dan untuk kepentingan apa. Wong menyaksikan bencana sedemikian rupa. Airmata saya lebih sering terjatuh. Kata-kata bungkam. Bahkan tak kuasa jua meminta tolong kepadaNya. Bukankah sesering dan setiap kali kita menyebut, mengagungkanNya .. bukankah … bukankah … ah, pastilah Yang Maha itu selalu tahu … tidak sepatutnya saya rasa mempertanyakan ini. Tidak sepantasnya.
Kalau gitu saya mau bertanya saja pada diri saya sendiri: “Hai .. Gog! Apa pentingnya kamu suka nangis. Apa pula itu sok kritis. Sok tahu. Kamu kan punya jiwa dan raga yang kuat. Intelek. Banyak tahu dengan cara-cara dan bagaimana sebaiknya harus berbuat. Ayo apa yang bisa kamu lakukan!”
Lae … lae … Duh, Gusti Pangeran ingkang Maha Welas … nyuwun daya. Nyuwun kekiatan ….
[]
Pondokaren
20 November 2010
: 15.46


 Bersalam-salaman. Berbagi sapa. Berbagi senyum. Berbagi bungah. Inilah adab kami, gotong royong itu punya nama.
Bersalam-salaman. Berbagi sapa. Berbagi senyum. Berbagi bungah. Inilah adab kami, gotong royong itu punya nama.




 Karena kami diancam
Karena kami diancam