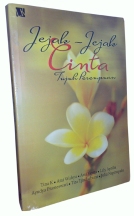Oleh Iwan Piliang
Serial Upin Ipin, diputar berulang di TPI. Ceritanya kuat, walaupun secara teknis animasi, visual tokoh utamanya hanyalah dua bocah kembar plontos, minimalis; bersekolah, bermain, berkehidupan di kampung. Literair penggalan pengalaman saya di industri animasi, berupaya lalu patah di tengah jalan mengindustrikan animasi di Indonesia. Padahal kemampuan animator kita, jauh lebih baik dari Malaysia. Sama dengan lebih unggulnya skill anak Indonesia di industri perminyakan. Setidaknya Dt. Noor M. Chalid, kartunis Kampong Boy, pernah ingin mengorder animasi ke saya. Pada 13 Agustus lalu rasa keindonesiaan kita seakan ditampar oleh ditembaknya kapal Patroli Departemen Kelautan RI di wilayah RI, oleh Polisi Perairan Diraja Malaysia. Mereka menangkap tiga petugas kita. Saya menyebut langgam Malaysia ini bagaikan Orang Kaya Baru (OKB) di Indonesia. Kata orang kampung saya, mereka ongeh—setingkat di atas congkak. Tarian Randai Sungai Geringging, tanah kelahiran saya, pernah pula diaku Malaysia sebagai keseniannya. Namun Upin dan Ipin tetaplah menghibur! Mana serial animasi kita?
TIGA anak saya lelaki. Mereka sepuluh, delapan dan tiga tahun. Dua anak tertua kini sudah menjalankan ibadah puasa penuh. Hiburan utama kami di saat makan sahur bersama keluarga di Ramadan kali ini menyimak penggalan serial animasi Upin-Ipin, produksi Malaysia disiarkan oleh TPI.
Di sebuah serialnya, Ipin membayangkan berbuka puasa melahap ayam goreng. Lalu kakaknya, Ros, mengajaknya berbelanja ke pasar. Kak Ros memberikan lembaran ringgit, sedianya dibelikan untuk dua tiga potong ayam sahaja. Namun Upin dan Ipin, justeru merasa dapat angin. Mereka membelanjakan semua ringgit ke aneka ayam; ayam golek, ayam madu, ayam goreng, ayam bakar, ayam pandan.
Di pasar mereka melihat Mail, teman sekelas, menjual ayam goreng kegemaran Ipin.
“Kau belilah ayam aku ni ‘Pin, emak aku buat, enaklah!” Mail berpromosi.
Si kembar itu pun sepakat membeli. Tak tanggung-tanggung, semua ayam goreng dagangan Mail bersisa, mereka borong.
Visual Upin dan Ipin menenteng beragam bungkusan serba ayam dengan riang pulang. Tinggallah Kak Ros manyun terperangah, segenap ringgit telah berganti ayam.
Di meja makan berbuka puasa. Meja penuh dengan hamparan piring berisi aneka penganan serba ayam.
“Kau habiskan itu semua,” ujar Ros ke Upin dan Ipin. Wajah Ros dongkol.
“Tak lah Kak, tak kuat lagi kami makannya.” suara Upin dan Ipin memelas.
Suasana di ruang makan di kampung melayu, Malaysia, itu. Opa—nenek—lalu menasehati Upin dan Ipin dengan suara khas, bijak, bahwa kalau lagi berpuasa, di siang hari, memang serasa semua makanan seakan terlahap, namun nyatanya di saat berbuka, sedikit sahaja dimakan, perut sudah berasa kenyang.
Khas duniak anak-kanak, khas Melayu.
“Betul, betul, betul!” ungkapan khas Ipin.
Ia acap mengulang ucapan lema betul, bentuk persetujuannya akan sesuatu.
Lalu anak Indonesia mengenallah budaya Malaysia melalui animasi. Berlanjut membanjirlah merchandising Upin Ipin, termasuk mewabah mainan tangkai es krim, diantaranya.
Lantas pertanyaannya, mana budaya kita, mana industri animasi Indonesia?

PANTASKAH saya bertanya?
Setelah mencoba berbisnis di jasa iklan sejak berhenti jadi wartawan dari majalah SWA pada 1989, dari 1993 hingga 1995, saya fokus memproduksi serial animasi. Alasan saya ketika itu sederhana saja. Bahwa menjadi pengusaha haruslah punya produk dan atau jasa yang masuk ke pasaran. Itu pengusaha!
Kalimat itu terus saya sosialisasikan di setiap menulis mengupas kewirausahaan hingga kini. Konon, kemajuan Cina dahsyat kini, tiada lain karena kegigihan membanjiri dunia dengan manca-ragam produk.
Nah setelah “capai” di jasa yang saya rasakan lebih banyak tangan “di bawah”, saya memilih industri tak dilirik orang ramai. Yakni serial animasi. Pilihan saya kala itu animasi wayang, dengan membuat karakter anak-anak, ada yang plontos macam Upin Ipin, namun berbaju wayang. Saya memilih judul Burisrawa, berdialek Batak.
Mengapa wayang? Sulit bagi saya kala itu membuat cerita berserial banyak. Cerita Kancil saja, untuk dijadikan enam episode masing-masing 24 menit—untuk siaran setengah jam—sudah seret kisahnya. Saya memilih Wayang Carangan, yang tak akan habis dikembangkan kisahnya hingga beratus serial.
Maka singkat kata, setelah sempat melihat-lihat ke Disney, AS, saya pun mengumpulkan animator 2D terbaik negeri ini, dan membenamkan segenap uang yang dihimpun seperak dua perak dari usaha selama lima tahun, lalu fokus membuat serial animasi.
Sesungguhnya serial animasi itu gampang menghitung bisnisnya. Harga penjualan paling murah serial itu per episode US $ 1.000, lalu jika kita sudah memproduksi 52 episode, untuk setahun, diputar seminggu sekali, maka per paket US $ 52.000. Untuk melego ke-1.000 stasiun teve menayangkan di pasar global sesuatu yang dapat dijangkau.
Maka jika seribu teve manca negara membeli, akan didapat US $ 52 juta, alias Rp 500 miliar lebih, belum termasuk pendapatan penjualan karakter untuk merchandising. Anggaplah pesimis, 10% saja jangkauan penjualan, masih diraih US $ 5,2 juta.
“Untuk meraih seribu televisi, bukan suatu yang sulit, karena di suatu negara televisi lebih dari satu, belum termasuk hak ulang siar,” ujar David C. Fill, Direktur Burbank, Sydney, pernah mengunjungi studio animasi saya awal 1995.
David pula yang melihat potensi Burisrawa dengan perbaikan penambahan dialog. Ia menyanggupi memasarkan ke Eropa, Asia, Timur Tengah. Amerika Serikat tidak bisa tembus, karena karakter yang kami buat terlalu tradisional.
Maka ketika satu episode serial Burisrawa yang kami produksi kelar, saya pun membuat sebuah event di Hotel Le Meredien pada awal 1994, membedah produksi kami. Hadir seratusan pakar, budayawan, kalangan DPR, pemerhati anak. Kritik dan pujian mengalir.
Episode pertama itu pula yang membuat Datok Noor M. Chalid—akrab dengan tokoh kartunnya: Lat—menerima saya di Kuala Lumpur, 11 Februari 1995. Ia menjemput saya ke bandara dengan Pajero, yang ia kemudikan sendiri. Ia mengajak ke sebuah klub eksekutif tak jauh dari Masjid Raya, Kuala Lumpur. Di sana sambil makan siang dengan nasi beralaskan potongan utuh daun pisang, kami saling tertawa, bagaimana serial Kampong Boy, dibuat di Kanada, sebagian proses dikerjakan oleh animator Filipina.
“Batang kelapa berdaun pisang, pisang berdaun kelapa. Pedati jadi macam kereta kuda kerajaan,” ujar “Lat“. Kami lalu terbahak-bahak, menertawakan para desain karakter Kanada tidak pula tahu beda kelapa dan pisang, juga pedati hanya gerobak, kayu segi empat ditarik sapi atau kerbau.
“Segera tahun depan, saya akan berkunjung ke studiomu, kita jajaki kerjasama produksi, karena di Indonesia biaya produksi rendah,” ujarnya.
Rencana Datok “Lat” itu tak pernah kesampaian. Sebab di penghujung 1995, seluruh dana produksi yang saya miliki dengan jumlah serial animasi kelar 6 episode, mencapai hampir Rp 2 miliar terbenam sudah. Pre Letter of Intent dari sebuah televisi lokal yang berkenan membeli dan menayangkan, tak kunjung kontrak. Padahal saya berkenan mereka beli di harga berapa saja. Toh sudah ada komitmen pasar global. Karena tiadanya kontrak, saya kesulitan mencari loan ke perbankan lokal.
Produksi yang rampung enam episode itu mustahil dipasarkan, karena untuk tayang setidaknya perlu 13 episode, dan untuk dijual ke pasar globali dealnya 52 episode satu paket, minimum 26 episode.
Maka khatam sebuah upaya membangun sebuah animasi dalam kerangka industri itu.
Sepuluh tahun silam kepada Agung Sanjaya, animator di Bali, memiliki studio mengerjakan bagian proses animasi untuk banyak produksi serial Jepang, seperti Dora Emon, Candy-Candy, bahkan untuk film animasi layar lebar Jepang, saya sampaikan ide untuk ke depan memproduksi serial Wayan dan Made.
Sebab dari Sanjaya saya mengerti bahwa Jepang tidak bakalan mendukung industri animasi negara lain. Karena itu salah satu credential asset mereka, baik sebagai industri, maupun penetrasi budaya. Di Bali orang kita hanya menjadi tukang yuntuk Jepang, sebatas meraih gaji tak seberapa.
Maka, ide tinggallah ide. Kini Indonesia, heboh Upin Ipin.
Mencari permodalan untuk bisnis kreatif di Indonesia amatlah sulitnya. Apalagi yang namanya venture capital riil yang saya teriakan sejak 25 tahun lalu, untuk dunia industri kreatif Indonesia, hingga kini masih isapan jempol belaka.
DI MEJA saya ketika menuliskan literair ini, menggeletak buku Undang-Undang Nomor 11, 2008, tentang Informasi Transaksi Elektronika (ITE). Di bagian halaman awalnya, ada tanda tangan seorang Dirjen Aplikasi Telematika, Depkominfo. Pada awal ia menjabat sempat saya paparkan potensi Indonesia di konten dan animasi. Karena, Departemen inilah salah satu yang sedianya mampu mengembangkan animasi menuju industri, bekerjasama dengan Departemen Perindustrian dan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
Namun belakangan hari, sang Dirjen boro-boro mengembangkan industri animasi untuk konten telematika, malah membuat UU ITE yang mengakibatkan ranah kehidupan seakan gonjang-ganjing, bahkan seorang ibu menyusui macam Prita Mulyasari, harus dibuikan tanpa bisa pamit ke anaknya yang lagi disusui.
Kala itu saya menggugat UU ITE ke Mahkamah Konstitusi (MK), seakan seorang diri. Kawan-kawan media kala itu belum ngeh. Sang Dirjen, di persidangan sempat membawa artis Azhari bersaudara, sehingga konten pasal 27 ayat 3 yang saya gugat, soal beratnya hukuman ihwal pencemaran nama baik, seakan beralih ke sisi privat artis yang harus dilindungi. Dan kuat dugaan saya sang artis datang ke MK dibayar dengan uang Departemen, uang rakyat.
Kini mantan Dirjen itu sudah pula menjadi Komisaris sebuah bank BUMN papan atas. Dilihat dari portofolio karirnya, mampu melompat-lompat dalam hitungan pendek; Sebelumnya Kepala PT Pos Sumut, lalu tak sampai setahun jadi salah satu jajaran pimpinan Percetakan Uang Negara RI (Peruri). Maka pahamlah saya, bahwa bicara dengan pejabat negara, menjadi seakan menghadapi tembok.
Di Departemen Perindustrian, saya pernah merintis pengadaan motion capture. Alat untuk meng-capture gerak, sehingga mempercepat proses produksi. Departemen manganggarkan untuk dua tahun uang negara Rp 3,7 miliar sesuai dengan alat asal Inggris yang saya rekomendasikan: 18 kamera infra red, real time.
Ketika turun anggaran tahun pertama Rp 1,7 miliar, eh, kawan di AINAKI (Asosiasi Industri Animasi dan Konten Indonesia), dimana organisasi ini saya salah satu pendiri—bahkan logonya pun goresan tangan saya sendiri—bersama sang Departemen, malah membeli kamera berkualifikasi sangat rendah dengan spesifikasi kualitas VGA, yang tak sampai Rp 200 juta didapat di pasaran. Hal ini harusnya diverifikasi KPK.
Dengan membeli peralatan dari Inggris, padahal tetap ada profit 5%, industri tertolong peralatan terpakai untuk kepentingan industri secara riil.
Dan di tahun berikutnya saya tak tahu lagi. Konon alat yang telah dibeli berkriteria VGA itu menganggur. Padahal setelah motion capture, saya mengharapkan negara mendukung pembelian jaringan komputer untuk merender: Rendering Farm.
Apa dinyana, wong motion capture gagal, apalah pula rendering farm.
Saya kemudian lebih memilih menulis untuk publik. Dari jauh saya amati banyak sekali sosok mengaku begawan di dunia animasi di Indonesia, tetapi belum ada yang mampu menjadi sebuah industri memproduksi 52 episode.
Maka ketika di event Indonesia ICT Award (INAICTA) 2010 ini ada animasi 3D Larjo, masuk sebagai pemenang, Riza Endartama, animator, lalu menjawab ucapan selamat saya di facebook-nya, “Iya kan berkat upaya abang juga dulu.” Ketika masih aktif di AINAKI dulu, kami memang sempat meminta usulan kawan-kawan animator membuat rencana serial. Larjo (singkatan Lalar Ijo) salah satu yang terpilih untuk dicarikan solusi menjadi serial, minimum hingga 26 episode, pada 2004 lalu.
Kini dalam hati terkadang ada rasa berkecil hati; apalah kita dibandingkan Malaysia kini dengan Upin Ipin saja kita telap.
Toh Larjo saja barulah berdurasi 5 menit, tidak pula sampai sepuluh episode.

Saya terkadang senyum dikulum. Menertawakan diri sendiri: tahu jalan menuju roma, apa daya tangan tak sampai. Jadi ingat sosok Jarjit Singh, acap berpantun di serial Upin Ipin, “Satu dua buah manggis, gagal tak usahlah menangis.”
He he he
Begitulah kawan-kawan, sebuah narasi tentang animasi yang tak kunjung menjadi industri di negeri ini. Rindu akan pemimpin negeri ini paham akan potensi dan peluang credential asset anak bangsanya.
Selamat merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan! []
Iwan Piliang, Literary Citizen Reporter, blog-presstalk.com