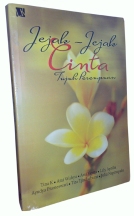Oleh Iwan Piliang, Literary Citizen Reporter
“Profesi wartawan tak bisa dibeli.” Budiman S Hartojo (BSH), wartawan senior dan penyair, mantan wartawan Tempo, ini, Jumat pekan lalu dimakamkan. Ia berpulang di usia 71 tahun. Teman, ayah, paman, sekaligus “lawan” diskusi, BSH, begitu ia akrab disapa, menjadi kamus berjalan wartawan muda. Sebuah penggalan kenangan bersama pendiri Persatuan Wartawan Indonesia Reformasi (PWI-Reformasi) ini; tauladan etika dan prinsip jurnalisme, tempat bersandar saling-silang belajar; antara senior dan yunior. Sebuah situasi nan kini sirna di meja redaksi media.
JUMATsiang menjelang shalat Jumat, 12 Maret 2010 Mendung menggayut. Matahari malu-malu dibalut awan. Hujan titik rintik. Keranda jenazah Budiman S Hartojo, kelahiran Solo, berpulang Kamis, 11 Maret 2010 pukul 14.22, itu, dibawa ke masjid di sebelah halaman taman rumahnya,di bilangan Jati Bening II, Bekasi, Jawa Barat.
Di saat itulah ingatan saya menerawang kepada sosoknya. Ketika saya pindah ke Jakarta 1979, dari Pekanbaru, Riau, semester akhir SMP, dan tinggal di bilangan Karet Belakang, Karet Kuningan, Jakarta Selatan. Saya tak menduga bertetangga dengan seorang wartawan Tempo, majalah yang edisi bekasnya suka saya bulak-balik, beberapa artikel kadang saya baca.
Menuju kelas 1 SMA, intensitas perjumpaan dan ngobrol dengan BSH meninggi. Apalagi kedua orangtua saya yang sudah duluan tinggal di Jakarta, sejak 1973, lebih dulu mengenal BSH dan isterinya Djati Budiman, sosok perempuan cantik, kelahiran Cirebon.
“Ibumu kalau bikin rendang enak sekali,” ujar BSH.
Entah karena pintar memuji, setiap ibu saya memasak, termasuk gulai kepala ikan, pastilah BSH tidak terlewatkan. Bahkan sup tulang tungkai sapi, yang berisi sum-sum, menjadi santapan kegemaran BSH. Bisa Anda bayangkan kolesterolnya? Sayalah kebagian mengantar ke kediaman kontrakannya. Sepenggalah saja jaraknya dari tempat kami.
Tukar-menukar penganan acap kali. Di jeda sowan itu, ada saja obrolan dengan BSH. Dari situlah satu dua bukunya, suka saya pinjam dari perpustakaan pribadinya. Banyak buku sastra, termasuk majalah Horison yang lama. Buku kumpulan puisinya tak pernah terlewatkan.
Intensi mengobrol dengan BSH, seingat saya ketika saya kelas dua SMA, soal pembredelan Tempo. Saya banyak mendengar beragam masalah liputan Tempo, yang tak disukai oleh rejim Ordebaru, kala itu. Juga soal internal majalah berita mingguan itu. Di hari-hari deadline, terkadang ia meminta saya tidur di kamar depan rumahnya, karena Tante Djati, seorang diri di rumah. Mereka tak punya pembantu, juga belum dikaruniai anak keturunan hingga akhir hayatnya.
MOBIL jeep Toyota Land Cruiser hardtop, coklat muda itu, baru saja dipasang rak di atas plafonnya. BSH menaikkan barang berukuran besar. Untuk ukuran badan kecil, pendek, dengan napas tersengal, tak tega melihatnya. Barang bawaan itu umumnya buku. Di medio 1980-an itu, BSH harus pindah ke Bandung, menjadi Kepala Biro Tempo, Bandung, Jawa Barat.
Mengenakan topi, bak Mafioso Italia, lengkap dengan jas kotak-kotak dengan bagian siku berornamen bulatan coklat, saya tertawa geli melihat sosok mafia kecil seakan tenggelam di balik lingkaran setir mobil yang besar. Kendati duduknya sudah diganjal bantal, badan BSH tetap tak kunjung meninggi.
Saya, ayah, dan ibu, melepasnya berangkat menuju jabatan baru. Jadilah kediamannya di Jakarta, bak rumah kami. Saya sehari-hari menunggui. Beragam buku koleksinya, menjadi santapan hari-hari. Ada dosa terasa di dada saya. Satu dua buku koleksinya ada yang terbawa, lalu dipinjam kawan, dan tak kembali. Dari sosoknya saya begitu memahami pentingnya literasi.
Dosa berikutnya, ketika mobil dinasnya sudah berganti dengan Daihatsu Charade merah. Suatu waktu ia pertama dapat jatah dari Tempo menunaikan hajji. Jadilah saya menemani Tante Djati, dan hari-hari wira-wiri dengan mobil merah itu, mejeng.
Pertemanan BSH dengan sumber berita luas. Kendati kritis terhadap pemerintahan Ordebaru, sosok macam almarhum Rudini, mantan Kasad, secara khusus mengirim ucapan selamat lebaran pribadi: foto Rudini dan isteri lengkap dengan tanda tangan pribadi, salah satu yang saya ingat dipajang di meja rumahnya. Ia berkawan dengan banyak orang, terutama seniman yang suka mangkal di Taman Ismail Marzuki (TIM). Ia memilih bersahabat dengan banyak anak muda.
Suatu hari di Bandung. Saya melihatnya bekerja. Suara mesin tik-ketak-ketuk. Suaranya keras, setajam tarikan pena kalau ia menuliskan sesuatu, termasuk tanda tangannya dengan haruf B dominan bertekanan. Entah karena melihat suara ketikan itu pula, hingga kini, kolega saya programmer Anthony Seger, selalu protes akan gaya saya mengetik di komputer.
Di Bandung saya melihat wartawan muda seperti Bambang Harimurti, kini Pimpinan Umum Tempo, dan banyak nama lain yang beredar di dunia penerbitan di Indonesia. Sosok Moebanoe Moera, kini Redaktur Pelaksana TRUST, dulu juga di Tempo, yang kebetulan berdiri di kanan saya saat men-shalatkan jenazah BSH, mengaku sebagai salah satu muridnya.
BSH mengingatkan saya akan ejaan. Hingga ia berpulang, penulisan ejaan saya tak pernah 100 % benar. Padahal, ejaan salah satu kunci profesional, begitu BSH selalu mewanti-wanti.
Maka ketika saya berkuliah di jurusan komunikasi massa, sebuah buku tipis Ejaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar, terbitan Balai Pustaka, yang menjadi acuan kami satu semester, hanya mengantarkan nilai kuliah di angka do-re-mi. BSH terpingkal-pingkal. “Maka jangan anggap enteng urusan ejaan,” ujarnya. Seingat saya, itulah tawa heboh sosok yang suka bercanda ini.
Acap pula dia memperlihatkan tulisan yang hendak ia serahkan ke redaksi Tempo, ke saya untuk dibaca. Dan selalu hampir tak ada cacad salah tulis. BSH mengingatkan menuliskan di menyatakan tempat, seperti di muka dipisah. Beda dengan penulisan dikerjakan, kata sifat. Hingga kini hal remah begini masih alpa dilakukan, tak terkecuali wartawan tua apalagi muda. Dia akan senang hati jika kita ikut mengoreksi tulisannya.
Suatu saat setelah pensiun di Tempo, BSH, masih kiri kanan berusaha bekerja menulis. Ia menulis untuk majalah Pantau, 2003. Naskahnya tak keberatan diedit oleh sosok muda seperti Andreas Harsono.
Kecuali ketika Andreas mempertanyakan, mengapa tak ada tanda-tanda kekerasan dalam ‘sarang teroris’ di Pesantren Ngruki?
“Lah saya itu reporter, apa yang saya lihat, itu yang saya tulis,” jawab BSH.
BSH bilang reporter itu profesi wartawan seumur hidup.
“Redpel, Pemred, itu kan hanya urusan jabatan.”
Tulisan BSH di Pantau, ditempatkan oleh kawan-kawan jurnalis sebagai salah satu literair yang bagus. Penulisan literair itu pulalah yang kemudian menjadi pendalaman saya.
“Dan menulis macam ini, bukan barang baru. Tahun dua puluhan, Adi Negoro sudah menulis dengan langgam literair dalam Buku Melawat ke Barat.”
KETIKA menginjakkan kaki melangkah ke masjid di Jumat pekan lalu itu, sambil mengiringi keranda jenazah BSH, ingatan saya masih melayang akan kediamannya. Kendati bersahaja, rumah itu didesain oleh arsitek Adhi Moershid, arsitek yang pernah mendapatkan Aga Khan Award atas karyanya untuk Masjid Said Naum, Jakarta.
Suatu hari masih di medio 80-an, ia memperlihatkan sketsa di kertas putih, goresan tangan sang arsitek. BSH bermimpi mewujudkan rumahnya itu, kendati tak tahu harus membangunnya melalui rejeki darimana. “Baguskan desainnya? “ katanya. Saya melihat matanya menerawang, bermimpi.
Di kediamannya itu pula pernah suatu hari saya menemani sosok almarhum Prof Dr. Saleh Poeradisastra, ahli sejarah cum sastrawan, yang sedang menulis buku. Ia ingin di tempat sepi tak terganggu. Saya naik angkot biru menemani Prof., Saleh ke sana. Jalanan becek berlubang. Kini walaupun sudah beraspal dan beton, jalanan seputar rumah masih ada bolong-bolong. Di rumah yang masih standar KPR kala itu, Buyung Saleh, begitu sang Profesor akrab disapa menyelesaikan terjemahan Darul Islam, misalnya.
Akibat perkenalan dengan Buyung Saleh, suatu hari saya ketika bekerja sebagai reporter di majalah Matra, membutuhkan referensi urusan asal muasal kata Menteng. Kami sedang melakukan liputan panjang kata Menteng. Amarzan, sebagai Redpel Matra, mengingatkan saya agar menemui Saleh. Benar saja. Saleh menyebutkan kata Menteng dari nama orang. Namun ia enggan dikutip dulu sebelum ada referensi.
Di suatu Kamis petang, Saleh bersandal jepit, membawa tas kresek berisi buku tebal berbahasa Belanda. Ia langsung menuju meja saya di mana Matra kala itu berkantor di Setiabudi Building II, Jakarta Selatan. Saleh dengan peduli menterjemahkan bagian penting bagi reportase saya. “Nama Menteng itu dari nama tuan tanah, Daeng Menteng,” ujar Saleh. Di saat VOC bubar, malamnya Gubernur Jenderal Belanda di Batavia, mengembalikan tanah-tanah tuan tanah.
Itulah gunanya senior, memberi arah, mengantarkan ke sumber yang bertanggung-jawab. Sejak saya berkecimpung tulis menulis, tak menemukan lagi bagaimana sosok macam Prof Saleh, punya tanggung jawab literasi besar sebagai sumber.
Dan pergumulan saya ke dunia tulis-menulis sebagai profesi, tidak terlepas dari katebelece BSH. Setelah saya menjadi reporter lepas majalah Swasembada (kini SWA), BSH membawakan surat untuk diberikan kepada Kemala Atmojo, Redaktur Pelaksana, di kantor majalah Zaman, sebagai bagian dari Tempo, kala itu di Proyek Senen. Di 1985 itu, Zaman akan berganti wajah menjadi Matra. Setelah mendapat penugasan dari Sori Siregar, Redaktur Zaman yang juga penulis cerpen, saya masuk sebagai list reporter lepas, hingga kemudian bekerja full di Matra.
Suatu petang, BSH memanggil saya, yang lagi mengetik laporan di Matra. Seperti biasa ia bersemangat dan tersenyum.
“Ini kenalkan Buyung, saudara juga.”
Sosok yang dikenalkan menjawab, Kemal.
“Ini Kemal Efendi Gani, dari Solo, orang Padang tapi lebih Jawa,” tutur BSH tertawa.
Ia menenteng Kemal bertemu Bondan Winarno – – kini terkenal dengan Maknyus itu — kala itu Redpel SWA, yang kantornya bersebelahan dengan kami. Tempo kala itu baru punya Gedung baru di seberang kami di HR Rasuna Said.
Kemal kini Pemimpin Redaksi SWA. Maka ketika saya melihat Bambang Halintar, Pemimpim Umum dan Perusahaan SWA, yang dulu juga di Tempo, hadir di antara pelayat, saya bertanya, ke mana Kemal?
Pertanyaan yang sama, agaknya, juga ditanyakan kawan-kawan kepada saya, “Ke mana Iwan?” di saat BSH dirawat di RS Thamrin, Jakarta Pusat.
Di saat saya di Abu Dhabi, Medio Februari 2010, SMS dari tanah air masuk. Eddy Mulyadi, mantan Sekjen PWI-Reformasi mengabarkan, “Jenguklah BSH, keadaannya mengkuatirkan.”
Dalam urusan SMS inilah saya sebagai anak, pernah melawan BSH, melarangnya berkirim SMS. Karena pernah menimbulkan salah pengertian di saat saya menjabat Ketua Umum PWI-Reformasi. Lebih jauh, saya pernah menghitung uang SMS yang dikeluarkannya untuk memotivasi wartawan jangan menerima amplop, termasuk menggerakkan organisasi PWI-Reformasi, jumlahnya sudah bisa mengganti mobil Daihatsu Classy Putih tuanya ke Kijang terbaru. Dan hingga akhir hayat, ia hanya mampu mengganti kelir mobil itu dari putih ke hitam. Bukan mobil baru.
Sekembali dari Abu Dhabi, bahkan telah tiga Sketsa saya tuliskan, saya tak kunjung juga menjenguk BSH ke rumah sakit. Entah mengapa jauh-jarak seakan melilit bak antara kutub utara dan selatan, langkah saya tak kunjung sampai ke rumah sakit. Lalu datanglah kabar melalui SMS bertubi-tubi dari kawan-kawan jurnalis, bahwa BSH sudah berpulang.
TANAH di pusara baru saja ditutup. Abdul Hakim, adik kandung BSH memberikan sambutan. Saya teringat akan bagaimana BSH mendidik adik kandungnya itu dulu bekerja. Abdul Hakim pernah dari satu rumah ke rumah lainnya mengukur jalanan Jakarta, mendagangkan buku terbitan Tira Pustaka. Seingat saya BSH hanya memberikan ongkos bis saja ke Takim, begitu kami menyapanya.
Saya pernah bertanya, makan siangnya bagaimana?
“Ia harus cari sendiri,” ujar BSH.
Maka sering ibu saya menawarkan makan seadanya kepada Takim, di saat bajunya lepek basah pulang kerja di era 80-an itu. Di Kamis malam di saat jam sudah menunjukkan 00.30, setelah 20-an tahun tak bertemu, Takim, menjabat tangan saya. “Sekarang saya jadi ustad,” katanya. Senyum dan tawa khasnya masih seperti dulu. Masih ingat dalam benak saya, hampir tiap malam Takim mengaji, membaca Al Quran.
Usai Takim berkidmat, kerabat diminta bicara terhormat. Toriq Hadad, Pemimpin Redaksi Tempo, mengenakan baju koko putih, berkopiah, di sebelah saya menatap, mengangguk, seakan meminta saya tampil. Adalah afdol Toriq mengucapkan kata akhir.
“Yang kita makam kan ini adalah guru kita, guru banyak kawan-kawan jurnalis,” ujar Toriq.
Sekelebat ingatan saya ke November 2008, di mana saya berada di liang lahat menutup pusara ibunda saya. Dari sudut mata, saya tatap BSH kala itu berkopiah haji, berjaket biru bersepatu karet putih, menatap nanar.
Ia ucapkan duka menjabat saya. “Ibu Agusti orang baik, pasti diterima di surganya Allah.”
Kala itu juga kalimat yang sama saya tabalkan dalam hati: Ya Allah, Budiman S Hartojo, orang baik, semoga Surga-Mu imbalannya. Amin.
Di Minggu, 21 Maret 2010, petang kami sekeluarga datang ke kediaman BSH. Menduga ada tahlilan, sebagaimana kebiasaan banyak dilakukan masyarakat. Ternyata menurut Tante Djati, isteri almarhum, mereka tidak mengadakan.
Keesokan paginya bangun tidur, isteri saya menangis sesenggukan.
Ada apa?
“Kok Pakdhe tidak ditahlilkan?”
Pakdhe adalah panggilan bagi ketiga anak kami terhadap BSH.
Saya jawab, pasti banyak orang mendoakan, banyak cara berdoa, termasuk malaikat akan mendoakan.
“Iya, ingat bagaimana dia bermain dengan anak-anak, mengajak anak-anak menggambar, sedih,” ujar Vivi, isteri saya.
Saya pun terbawa perasaan, bertanya dalam hati, mengapa sepi kawan dan kerabat mengantar BSH ke pusara, padahal begitu besar namanya? Jarak, waktu, dan kesibukan, telah membuat segalanya jauh. Sama dengan sok sibuknya saya, sehingga alpa hadir di saat Oom Bud – – begitu saya menyapa – – masih dirawat. []
Tulisan ini dapat pula dibaca pada blog penulisnya, di: http://blog-presstalk.com



 Bagi jurnalis muda, nama Halim HD belumlah dikenal secara luas. Maklum postur tubuhnya yang menyerupai ’biksu’ Shaolin ini tak banyak bicara dihadapan para wartawan muda, khususnya di Solo. Tapi bagi para pewarta senior, nama Halim tak asing lagi. Meski berpenampilan tak mencolok, ia toh tetap dikenal oleh para jurnalis ’kaplak-awu’ sebagai ’pengembara’ budaya, melanglang dari kota-ke-kota. Networker kebudayaan dan penulis, tinggal di Solo dan Makassar.
Bagi jurnalis muda, nama Halim HD belumlah dikenal secara luas. Maklum postur tubuhnya yang menyerupai ’biksu’ Shaolin ini tak banyak bicara dihadapan para wartawan muda, khususnya di Solo. Tapi bagi para pewarta senior, nama Halim tak asing lagi. Meski berpenampilan tak mencolok, ia toh tetap dikenal oleh para jurnalis ’kaplak-awu’ sebagai ’pengembara’ budaya, melanglang dari kota-ke-kota. Networker kebudayaan dan penulis, tinggal di Solo dan Makassar.