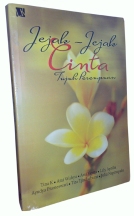( sambutan buku Puisi ‘Serangkaian Tunggu’ Penyair Helena Adriany )
Oleh Syaiful Alim
Saya belum punya buku puisi ‘Serangkaian Tunggu’ Penyair Helena Adriany. Tapi biarlah ini jadi awal mula apresiasi utuh ketika saya memiliki buku itu nanti.
Teks Sajak:
“duh”
I.
setiap pagi aku duduk di gerbang memandang matahari
padahal aku tahu gerbang membuka menjelang petang
II.
ada sebuah kertas di sampingku
tetapi mengapa aku menulis di saputangan
III.
sebaiknya kuikat rindu di luar pintu kamar
sebelum kau pikir aku lupa mematikan lampu
Balikpapan, 03 January 2010
Kaji Puisi: Membaca “duh” Penyair Helena Adriany: Kerinduan yang Berpeluh
SAJAK selalu lahir dari kegelisahan. Entah itu kegelisahan yang bersumber dari dalam diri atau luar diri sang Penyair.
SAJAK kuat dan abadi dipicu oleh kegelisahan. Kegelisahan menjadi pemantik tenaga puitik untuk menembakkan kata-kata.
PEMIKIR dan PENYAIR Robert Frost menyatakan bahwa sajak itu lahir dalam kondisi resah gelisah, ketidaknyamanan, dan ketidakmestian hidup. Lalu dia menyebutkan beberapa misal, yaitu marah pada keadaan yang salah, rasa cemburu, sakit rindu, juga patah hati.
“a poem, begins as a lump in the throat, a sense of wrong, a homesickness, a lovesickness,…it finds the thought and the thought finds the words.”
KETIKA itulah sajak bisa jadi alat perjuangan atau sebagai jalan meringankan beban yang tak tertanggungkan itu.
Memang, puisi tidak seperti sepiring nasi yang mengenyangkan perut pengungsi, puisi tidak seperti selimut yang menghangatkan orang kedinginan, puisi tidak seperti setetes obat merah yang menutup luka, puisi tidak seperti seoles minyak angin yang menyembuhkan perut kembung, puisi tidak seperti perban untuk melindungi luka dari kuman, puisi tidak seperti pakaian yang melindungi tubuh dari sengatan matahari, puisi tidak seperti pasir, koral, semen, batubata dan seng yang menegakkan cagak rumah. Tetapi puisi bisa menjadi cahaya kala gelap, pengingat kala lupa, penggedor kala teledor, pengobat kala sakit, penguat kala sekarat, jamu kala jemu, pemicu kala buntu, pemacu kala galau, penghibur kala hancur, istri kala sepi.
Penyair Subagio Sastrowardoyo pernah menulis puisi berjudul ‘sajak’ yang berkenaan dengan peran atau fungsi sajak bagi kehidupan.
“Ah, sajak ini,
mengingatkan aku kepada langit dan mega.
Sajak ini mengingatkanku kepada kisah dan keabadian.
Sajak ini melupakanku aku kepada pisau dan tali.
Sajak ini melupakan kepada bunuh diri”
***
Sebelum saya memasuki tubuh sajak, maka izinkan saya menyentuh dulu judul yang menjadi pintu.
Sungguh menarik apa yang diajukan oleh Penyair Helena Adriany dengan judul ‘duh’ ini. Apakah ‘duh’ sama dengan ‘aduh’? dimana letak gores perasaan keduanya?
ADUH. Kata ‘aduh’ bisa meloncat dari bibir jika tubuh atau bagian (seluruh) tubuh kita meradang kesakitan, misalnya ditusuk atau tertusuk peniti atau duri. Kata ‘aduh’ bisa hadir dari bibir ketika terpesona dengan sesuatu atau seseorang yang menakjubkan. Seperti ucapan, “aduh, tampannya penyair ini”. Kata ‘aduh’ juga bisa melesat dari bibir jika tersentak oleh sebuah kesalahan, kesalahan yang melahirkan penyesalan. Seperti ucapan orang yang terlambat datang di sebuah acara, “aduh, kenapa saya tidak dari tadi ke sini, pembicaraannya menarik sekali” atau ucapan kekasih, “aduh, kenapa dulu aku tidak menerima lamaranmu, maafkan aku”.
DUH. Huruf ‘A’ telah hilang dari tubuh ‘aduh. A yang menjadi pemantik telah lenyap ke dimensi yang senyap, sepi, sunyi. Apakah ‘A’ yang hilang ini mempengaruhi arti? Pasti dan tentu. ‘A’ di kata ‘ADUH’ adalah timbul dari sebuah kesengajaan si aku lirik untuk memaknai apa yang dirasakan. Sedangkan A yang hilang dari kata ‘DUH’ menyiratkan sebuah sikap yang ditetaskan dari luar kesadaran. Kesadaran formalistik telah sirnah ke dalam dimensi yang tak berbatas. Apa yang terjadi? Adalah perasaan yang utuh dan terombang-ambing dengan sesuatu atau seseorang yang membayangi diri si aku lirik. Ia adalah perkawinan antara kesakitan dan penyesalam. Namun perkawinan itu dibalut dengan selubung jiwa yang melambung, ngelaut, ada kehendak untuk terus meneguk kesakitan itu, tapi di sisi yang lain juga ada kehendak untuk menyesali apa yang sedang dan telah terjadi. Tapi penyesalan itu ditolaknya dengan halus. Sebab jika dia menyesal, berarti dia telah terbunuh oleh perasaannya sendiri. Lebih baik membiarkannya dan terus terjadi. Ada harapan yang kelak dipeluknya dalam pertemuan. Harapan yang dicicil dari kerikil-kerikil kesakitan membayangkan dan menghadirkan kekasih. Itulah yang disebut dengan rindu atau kerinduan. Rindu memang pedih. Tapi perjumpaan mengobati. Rindu memang ngilu. Namun pertemuan yang menyembuhkan.
SUNGGUH. Saya lebih bisa menikmati ‘duh’ penyair Helena Adriany ini dengan ‘kerinduan berpeluh’. Sebuah kerinduan yang meletihkan, melelahkah. Seolah si aku lirik menempuh perjalanan jauh untuk merangkai pucuk-pucuk rindu yang kelak mekar dan jadi mawar. Mawar pun berduri.
SUNGGUH. Saya lebih bisa menikmati ‘duh’ penyair Helena Adriany dengan ‘kerinduan berpeluh’. Penantian yang begitu lama akan kedatangan kekasih itu telah meluruhkan keringat kehangatan yang berlelehan di sekujur tubuh. Layaknya seorang pendaki gunung, peluh yang berlelehan itu dinikmati sampai mencapai puncak yang dikehendaki. Ia tak kan beranjak dan turun lagi ke bawah. Ia terus melangkah dan melangkah.
“duh”
I.
“setiap pagi aku duduk di gerbang memandang matahari
padahal aku tahu gerbang membuka menjelang petang”
Ini saya sebut ‘laku rindu pertama’.
Imaji kita langsung diseret oleh penyair berlesung pipit ini: seolah kita melihat dari dekat atau jauh seorang yang duduk di bangku atau di segunduk tanah memandang cerah sinar matahari. Apa yang hendak disuarakan oleh si aku lirik yang dipeluk rindu dalam larik sajak ini?
Saya kira kata ‘gerbang’ adalah kunci dari pembacaan larik cantik ini. Saya lebih condong memaknai ‘gerbang’ sebagai ‘pintu waktu’. Pintu waktu yang sudah menjadi kesepakatan antara kedua kekasih. Pintu waktu itu sebagai jalan masuk untuk saling berpelukan, meredam dendam rindu.
Memang seorang perindu itu berperilaku aneh dan unik. Keanehaan itu digerakkan oleh rasa gelisah yang menujah dada. Seperti yang kita rasakan dari keanehan yang dilakukan si aku lirik pada larik ini: sudah tahu gerbang itu membuka menjelang petang, tapi tetap saja menunggui sang kekasih semenjak matahari terbit. Betapa peluh penantian itu.
“setiap pagi aku duduk di gerbang memandang matahari”
Dan ‘matahari’ itu berperan sebagai latar saja. Bukan menjadi matahari yang bermakna konotatif. Matahari di situ seolah jadi saksi, juga jadi pelampiasan kegelisahan sang perindu (si aku lirik). Pagi dan matahari diajak ikut oleh si aku lirik untuk menanggung kegelisahan yang menggunung di dada itu.
Saya terkenang Penyair Besar Chairil Anwar yang begitu jeli dan lihainya memasang benda-benda alam ke dalam tubuh sajak-sajaknya. Seperti terlihat pada puisi di bawah ini.
AKU BERADA KEMBALI
Aku berada kembali. Banyak yang asing:
air mengalir tukar warna, kapal-kapal, elang-elang
Serta mega yang tersandar pada khatulistiwa lain;
rasa laut telah berubah dan kupunya wajah
juga disinari matari
lain.
Hanya
Kelengangan tinggal tetap saja.
Lebih lengang aku di kelak-kelok jalan;
lebih lengang pula ketika berada antara
yang mengharap dan yang melepas.
Telinga kiri masih terpaling
ditarik gelisah yang sebentar-sebentar seterang
guruh.
Dari sajak di atas nampak betapa air, kapal, elang, mega dimasukkan Penyair untuk memperkukuh tubuh sajaknya. Kesemua benda alam itu memang sengaja diletakkan, dan pasti dengan maksud tertentu. Misalnya sebagai penggambaran bahwa si aku lirik sedang tercabik dan lengang memandang laut yang dibalut air biru, kapal-kapal yang berlabuh-berlayar, elang-elang terbang menghiasi angkasa.
“padahal aku tahu gerbang membuka menjelang petang”
“padahal aku aku tahu…”
Ada tiga isyarat yang mengeram dalam larik ini. Pertama, sudah adanya nota kesepakatan yang dibuat oleh kedua kekasih. Kedua, adanya perasaan getir yang menyesakkan dada si aku lirik yang menunggu itu. ketiga, pengorbanan cinta.
Duduk sejak pagi memandang matahari sementara gerbang terbuka menjelang petang hanya bisa dilakukan orang kangen yang sejak pagi dilanda gelisah berharap suatu pertemuan. Sebuah pertemuan yang ditentukan waktu yang disepakati itu, yaitu ketika matahari terbenam dipukul malam.
II.
“ada sebuah kertas di sampingku
tetapi mengapa aku menulis di saputangan”
Ini saya sebut ‘laku rindu kedua’.
BETAPA GEMILANG larik sajak ini. Saya mencium aroma pengalihan fungsi sebuah benda. Sang penyair telah melakukan perubahan fungsi atas benda ‘saputangan’ itu.
Adalah menarik menelisik perubahan fungsi atas ‘saputangan’ itu – dari seulas saputangan menjadi benda lain yang bisa difungsikan untuk menulis. Saputangan yang biasanya untuk menghilangkan peluh atau kotoran debu yang lengket di tubuh, kini jadi benda yang dipakai nulis.
Sebenarnya apa yang terjadi dengan si aku lirik dalam larik sajak ini? Kenapa ia menulis di saputangan? Apakah yang dimaksud kerja ‘menulis’ di sini?
“ada sebuah kertas di sampingku
tetapi mengapa aku menulis di saputangan”
Sudah jamaknya seorang perindu itu gelisah. Ketika kegelisahan makin menujah, maka airmata yang menggantikannya. Airmatalah yang berbicara. Apakah yang dibutuhkan perindu yang airmatanya bercucuran berceceran di lantai? Kertas atau saputangan? Bisa kertas bisa saputangan. Kertas untuk menulis sajak, misalnya. Saputangan untuk membasuh basah airmata.
Tapi kenapa si aku lirik lebih memilih saputangan?
HIDUP adalah pilihan. Saya menduga saputangan terpilih karena “efek kegunaan” yang mengeram di diri saputangan. Saputangan lebih berdaya guna meniriskan tangis ketimbang kertas.
Tapi kenapa sang penyair menggunakan kata kerja ‘menulis di saputangan’…?
Pada hakikatnya seorang perindu yang membasuh basah airmatanya itu adalah menulis. Setiap usapan adalah pembentukan kata. Kata-kata yang meneterjemahan rindu itu. bebutir airmata yang mengalir itu menulis rindu.
(kasihan sekali ya si kertas itu, tak terpakai, sini kupakai nulis puisi )
III.
“sebaiknya kuikat rindu di luar pintu kamar
sebelum kau pikir aku lupa mematikan lampu”
Ini saya sebut ‘laku rindu ketiga’.
ALANGKAH memikat larik terakhir puisi Penyair Helena Adriany ini. Di sini sang penyair dengan jelas memunculkan kata ‘rindu’ dan menyebut yang dirindu itu dengan ‘kau’. Ini semacam gerak ledakan kerinduan yang dipendam dan diperam di dada.
“sebaiknya kuikat rindu di luar pintu kamar”
Saya terpikat dengan bahasa kata kerja penyair ini: kuikat. Begitu pintar dan cantiknya sang penyair memainkan atau memutar logika pembaca: mengikat rindu? rindu seolah hidup dan berleher. Agar rindu itu tidak lari, maka diikat pada sesuatu. Juga supaya seusai bangun tidur, si aku lirik bisa melepas ikatan rindu itu, dan melampiaskan kegelisahannya kembali.
LALU kenapa rindu diikat? Berbahayakah pada diri si aku lirik?
Saya tertarik dengan apa yang dikatakan para sufi bahwa rindu itu bercahaya, bersinar begitu terangnya, sehingga mereka silau, lalu menuju gua-gua memadamkan cahaya itu dengan dzikir kepadaNya. Begitu juga dengan rindu dalam puisi ini: rindu itu bersinar alangkah terangnya. Sehingga lekas-lekas si aku lirik mengikatnya (memadamkannya) di luar pintu kamar.
Berbahayakah rindu yang bersinar terang itu pada diri si aku lirik?
TENTU dan PASTI berbahaya. Rindu saya asosiasikan sebagai lampu di ruang kamar tidur. Lampu harus dipadamkan dahulu jika ingin tidur pulas. Begitu juga dengan rindu yang memancar sinar itu. si aku lirik ‘mengikatnya’ karena mencoba menenangkan kegelisahan yang menderanya sejak pagi.
“sebaiknya kuikat rindu di luar pintu kamar
sebelum kau pikir aku lupa mematikan lampu”
***
DEMIKIAN tafsir sajak ‘duh’ Penyair Helena Adriany ini. Sebuah tafsir sederhana dari seorang perenang buta, syaiful alim, di lautan yang penuh gelombang dan ombak. Semoga tafsir saya ini salah atau lepas dari niat mula Penyair ini menuliskannya. Tapi yang perlu dipegang adalah bahwa tidak ada tafsir mutlak di dunia ini. Seperti apa yang terkata dalam sajak di bawah ini.
“Setiap hendak kutangkap
Ia lolos dari dekap
Tak mampu menampung rasa
(sajak yang tak peduli, subagio sastrowardoyo)
Helen, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap airmata yang mengalir dari mataku seusai menelaah sajakmu? Pinjamkan aku saputanganmu.
[]
Khartoum, Sudan, 2010.
Syaiful Alim
Penulis Novel ‘Kidung Cinta Pohon Kurma’