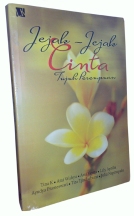Oleh Iwan Piliang, Literary Citizen Reporter
Rabu , 7 April 2010, azan subuh berkumandang, gempa di Simeuleu, Aceh, berdentang. Musibah lagi datang: Nun di Mamuju, Sulawesi Barat, sudah dua kejadian, anak miskin tak terawat ber-ulat. Di Topik Siang ANTV, bayi 14 bulan luka berbelatung kepala tak bisa berobat. Andai saja sudah sejak 20 tahun lalu bangsa ini memiliki negarawan; Presiden Negarawan; Menteri Keuangan Negarawan, segenap warga Depkeu negarawan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mafhum, maka perampokan bangsa melalui Transfer Pricing (TP), tidak sampai menghisap belulang, pemandangan bayi berulat tak terawat lewat; segenap musibah bantuan ada melimpah; kecerdasan generasi meningkat. Kini? Negarawan oh negarawan ke mana Anda? Kian keblinger DPR berapat dengan DJP,mengusulkan out sourcing orang pajak. Padahal salah satu inidikasi korupsi tajam di sistem teknologi informasi DJP, akibat di-outsoucing. Mengapa anggota DPR tidak instropeksi diri, laku membuat UU, pengemplangan pajak bisa dinego?
SELASA petang di studio QTV, Citra Graha, Lantai 11, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat.. Sebuah kehormatan bagi saya sebagai pemandu talkshow indie Presstalk, Achsanul Kosasi, Wakil Ketua Komisi XI DPR, berkenan tampil. Sejak sebulan lalu, saya memintanya bergabung membicarakan urusan pajak, jauh sebelum kasus Gayus Tambunan membuncah. Topik kami fokus ke urusan Transfer Pricing (TP); sebuah urusan kewajaran dalam bertransaksi, yang dibuat menjadi sangat tidak wajar untuk menghindari pajak. Premis jernih TP.
TP itu, dilakukan para perusahaan besar, PMA, perusahaan lokal, yang seharusnya wajar menjadi tampak tidak wajar. Saya juga sedang melakukan verifikasi, BUMN pun latah melakukan, lalu jika BUMN melakukan, dikemanakan untung yang “ditipkan” ke perusahaan afioliasi itu?
Siapa yang menikmati, sipa yang makan?
Untuk memudahkan pemahaman TP. Contoh harga gula sekilogram Rp 5.000, tapi oleh sang perusahaan dijual ke perusahan dalam group afiliasi ke luar negeri Rp 2.500, di pembukuan. Perusahaan afiliasi itu umumnya di negara bebas pajak, seperti Mauritius, Cayman Island. Produk gulanya secara riil masuk ke pasaran bebas di harga Rp 5.000. Untung sudah disembunyikan Rp 2.500.
Corak permainan pat-gulipat di TP ini manca ragam. Urusan membebankan biaya di luar negeri dipikul perusahaan lokal Indonesia, misalnya. Untuk contoh ini sudah saya tuliskan pada Sketsa sebelumnya, seperti indikasi dilakukan oleh; PT Toyota Motor Manufaktur Indonesia (TMMI), PT Kraft Indonesia, PT Hyatt Indonesia, di antara ribuan perusahaan kini bersidang banding di Pangadilan Pajak.
“Jujur selama ini kami tidak mengamati soal transfer pricing. Yang kami lihat Rp 600 triliun APBN dari pajak, lalu peningkatan jumlah wajib pajak mencapai sepuluh juta, sebuah prestasi,” ujar Achsanul.
Tranfer pricing (TP) memang cuma istilah. Pengertiannya, sesungguhnyalah urusan kewajaran bertransaksi. Masing-masing perusahaan membuat neracanya rugi. Untung disembunyikan. Biaya diperbesar. Impor harga ditinggikan.
Komponen biaya tak masuk akal, termasuk membebankan royalti hak cipta dalam sebuah angka tambun; Pada kasus royalti, misalnya, indikasi tajam pada merek Susu Bendera, bangsa harus membayar Rp 100 miliar setahun setidaknya ke luar negeri.
Pada kasus royalti ini, Australia pernah palak kepada kelakuan Toyota. Tercatat archive di google, sebagaimana diingatkan pembaca Sketsa di Kompasiana.com. Modus transfer pricing ini bukan hal baru bagi Toyota. Pada 2004, diberitakan di media Australia kalau Toyota sedang berselisih dengan kantor pajak Australia. Kantor pajak menagih sampai satu miliar dolar Australia. Dan hal yang sama terjadi juga awal 90-an. Lihat: <http://www.theage.com.au/articles/2004/06/18/1087245116983.html.>
Jika saja Grup Toyota Astra melakukan TP di Indonesia tahun-menahun tambun, bukan isapan jempol jika puluhan bahkan ratusan triliun hak penerimaan negara terindikasi telah mereka hub-balahap-kan. Pembaca Sketsa lain mengatakan, “Jika hal itu memang sudah terjadi, betapa kejamnya, bagaimana negara ini telah memberikan banyak fasilitas dan kemudahan di sektor otomotif. Sebuah penghianatan.”
Bahkan sosok Amin Appa, pembaca Sketsa di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab menuliskan, “Kendati sudah ada AFTA sekalipun anehnya harga mobil tetap saja dua kali lipat di Indonesia dibanding di sini.”
Amin Appa, yang beristerikan sosok wanita Bosnia, lebih lanjut menuturkan:
“Mengingat sumber kemiskinan rakyat Indonesia adalah karena banyaknya uang pajak yang menguap, maka belajarlah ke Bosnia yang baru saja porak poranda akibat perang saudara, “ tulis Amin pula, “Bosnis kini bangkit dan bukan hanya membangun tapi juga telah berhasil membebaskan pembayaran sekolah dan kulliah dari semua tingkatan dan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warganya. Sumber dananya hanya mengandalkan pembayaran pajak sebesar 17% bagi pajak penjualan dan produksi.”
“Bosnia tidak punya kekayaan alam seperti Indonesia. Tetapi rakyatnya bisa sejahtera walau belum sampai ke taraf negara-negara maju di Eropa. Bosnia berhasil karena adanya pengawasan dan kesadaran tinggi untuk kesejahteraan bersama.”
Sumber utama pemiskinan Indonesia, memang, saya indikasikan dominant dari pajak yang kabur di TP. Soal volume besarannya yang terindikasi TP pada 2009 mencapai Rp 1.300 triliun, jernih dan jelas perhitungannya.
Bukan isapan jempol.
Mengkalkulasinya gampang saja, jumlah transaksi perdagangan pada 2009 mencapai Rp 2.400 triliun, menurut pejabat di DJP, sebanyak 60% di lingkup masalah TP.
Mengapa TP menjadi-jadi terjadi?
“Jujur, kami alpa mengamati,” kata Achsanul.
Kenyataan di lapangan baru ada seksi TP di DJP pada 2007. Padahal laku TP sudah membumi di negeri ini sejak 20 tahun. Atas dasar inilah saya mengatakan, volume uang yang diributkan di kasus Gayus Tambunan, hanyalah urusan di receh, masalah kulit ari. Di banyak urusan, bangsa ini acap membunyikan urusan remah. Padahal uang negara raib menambun di soal TP.
“Berarti uang pajak untuk APBN selama ini masih berkutat penerimaan dari pajak publik, dari dunia usaha besar-besar itu belum optimal dan atau tak dioptimal oleh sang pengusaha yang telah mendapatkan pasar dan berbagai kemudahan?” ujar Achsanul heran.
Tepat!
Menjadi tidak tepat adalah ada dua hal. Setidaknya, UU perpajakan bermasalah. Pertama UU 28 tahun 2007, pasal 36A; pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Pasal ini telah membuat semangat kerja staf DJP kecut.
“Bener-bener bikin males, sudah capek menghitung, jika salah, kena sanksi lagi,” ujar Sanusi, staf di kantor pusat DJP.
Kedua soal UU 36, 2008, pasal 44, yang membolehkan penggelapan pajak dapat diselesaikan di luar pengadilan, dengan denda maksimum mencapai 400% dari pajak yang digelapkan. UU demikian membuat kejadian macam Gayus Tambunan, menjadi kekuatan para pihak; mulai wajib pajak, konsultan pajak, pengadilan pajak, hakim, kepolisian, dapat bermain.
Wong, edan tenan, boleh nego!
Sudah seharusnya kedua UU itu menjadi topik perhatian. Namun ketika Rabu petang saya lihat di televisi: Komisi XI DPR ketika memnggil Dirjen Pajak, seorang anggota dewan dengan entengnya mengusulkan langkah ou- sourcing SDM pajak. Fakta di lapangan kasus komputerasi, teknologi informasi dan data baase DJP, yang dilakukan tender nya di era Darmin Nasution menjadi Dirjen Pajak, terindikasi kuat bermasalah.
Apatah pula kini semua urusan pajak di out-sourcing?
“Kami untuk mengubah atau menambah satu entri data saja, untuk kepentingan formulir, pihak ketiga yang menjalankan system IT Pajak, menolak,” kata Sanusi, karyawan kantor pusat DJP.
Itu artinya kontrol terhadap data segenap wajib pajak ada di tangan pihak ketiga.
Mak!
Kenyataan ini mitrip pula dengan ap yang terjadi Depertemen Tenaga Karja RI. Siluruha input data base diserahkan kepada pihak ketiga. Sehingga semua data TKI, dimiliki oleh pihak ketiga.
Sekarang urusan data uang penerimaan negara dari pajak, ada pula digenggaman pihak out-sourcing.
Tidak salah, memang.
Tetapi jika pihak DJP, dibuat macam menumpang di mana haknya sendiri seakan ditutup demi perbaikan, menjadi tanya, mengapa negara kemudian dikebiri?
Di pengadilan bagaikan tamu, di urusan teknologi informasi, menjadi penumpangh, di undang-undang dikebiri, bisa Anda bayangkan, kini betapa muaknya sesungguhnya menjadi karyawan DJP.
Kemuakan itu, saya dapat pahami, apalagi kini sejak kasus Gayus Tambunan, sebagaimana diungkap Dirjen pajak di depan Komisi XI DPR Rabu petang, “Staf kami di jalanan lupa mencopot tanda pengenal, lalu diteriaki maling.”
Padahal maling besarnya di ranah dunia usaha.
Di Apa kabar Indonesia malam, lain lagi diperdebatkan, soal kerahasiaan wajib pajak yang harus dilindungi melalui UU 34. Pembicara antara lain Fuad Bawazier, yang di Sketsa sebelumnya saya singgung soal kiprahnya, juga Ichsanodin Noorsy, mantan anggota DPR.
Mereka lupa jika wajib pajak, berani mengugat ke pengadilan, dan pengadilan adalah ranah publik, maka di saat itulah dia juga siap membuka diri. Kudu! Apalagi pasal 50 ayat (1) UU No 14 tahun 2002, jelas mengatakan bahwa pengadilan pajak terbuka bagi publik.
Logikanya, jika berani berperkara, maka berani buka-bukaan ke masyarakat umum. Jika enggan buka-bukaan, bayar pajak dengan benar, hak rakyat jangan ditelap.
Begitulah Sidang Pembaca, sebagaimana pesan yang disampaikan seorang pejabat di Menko Perekonomian kepada saya, Sketsa TP dan DJP ini, jika saya tuliskan dalam lima tahun tak aka nada habisnya.
Karena, memang, esensi soal lari ke mana-mana. Upaya anggota DPR membuat UU melenceng, bak lain angguk lain ilalang. Kepada Achsanul saya tanyakan, apa karena 2/3 anggota DPR pengusaha?
Dan atau yang belum menjadi pengusaha kini juga merangkap jadi pengusaha?
Lain lagi menkeu Sri Mulyani.
Sejak kasus Gayus, Menkeu terindikasi tajam reaktif. Maka segenap staf yang harus memperjuangkan hak negara, hak rakyat di pengadilan pajak, kini menjadi tidak tersedia. Contohanya untuk staf banding semacam Gayus, dibebas-tugaskan tanpa terkecuali. “Sementara persidangan harus berjalan, setiap hari,” ujar Sanusi, staf DJP.
Sampai pada kalimat Sanusi tadi, maka Rabu, 7 April 2010 pagi saya ke pengadilan pajak lagi.
JALANAN di Rabu pagi di menjelang pukul 10.00 tidak terlalu macet. Seperti biasa di Gedung Sutikno Slamet, Depkeu, bak sudah saya tulis di Sketsa terdahulu, tamu harus mendaftar dulu, meninggalkan KTP.
Kali ini, pertanyaan dua gadis penerima tamu lebih rinci. Di samping dua petugas keamanan bersafari hitam mengamati saya.
“Mau ke mana Pak?”
Lantai Sembilan, jawab saya.
“Bapak dari PT apa?”
Modus baru rupanya.
Bertanya asal perusahaan sang tamu.
Apakah jika bukan berkepentingan, bukan peserta sidang pajak tidak boleh naik?
Apa Depertemen Keuangan tidak membaca UU, seorang jelata pun asal rakyat Indonesia boleh masuk ke sana. Gedung itu dibiayai rakyat, mereka digaji rakyat, dan urusan di pengadilan pajak bagi kepentingan rakyat!
Dari pada saya mengaku sebagai Citizen Reporter, anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia, blogger blog-presstalk.com, mantan ketua Umum PWI-Reformasi, akan panjang urusan. Secepat kilat saya sebut saja berasal dari salah satu grup sebuah perusahaan. Asal ingat, asal ucap.
Mereka memberikan tanda pengenal tamu.
Ada saja improvisasi baru, untuk “menghambat” kalangan media masuk ke Pangadilan Pajak.
Di lantai 9 saya amati, kursi tamu masih ada tersisa kosong. Biasanya selalu penuh.. Pintu-pintu ruang sidang, yang persidangannya sedang berjalan memang kini masih terus tampak dibuka. Kenyataan ini jangan sampai hangat-hangat tai ayam. Bila bulan depan ditutup lagi, akan menjadi laku basi.
Hendak naik lift saja kini filter sudah bertambah.
Saya lihat di papan dinding, ada daftar hampir 40 perusahaan bersidang. Mereka di antaranya: PT Bakrie Pasaman Plantation, PT Sinar Mas Air, Halliburton Indonesia, Toshiba Visual Media, dan banyak lainnya.
Di saat duduk mengamati daftar sidang hari itu, seorang wartawan Media Indonesia masuk. Menyandang ransel hitam, ragu-ragu. Saya mendengar pertanyaannya ke seorang di belakang saya. Saya berdiri menghampiri. Saya perkenalan diri.
Wartawan itu mengaku membaca Sketsa saya di milis jurnalisme di Yahoogroups. Saya minta ia yakin saja masuk ke salah satu ruang sidang mengikuti acara persidangan. Ia masuk ke ruang sidang IV. Saya menguping di ruang sidang II. Di ruang sidang dua, saya melihat bukti implementasi kebijakan reaktif Menkeu Sri Mulyani. Wajib pajak ada. Namun wakil petugas banding dari DJP tak ada. Bagaimana mereka bisa datang, wong Menteri-nya telah menon-aktifkan mereka semua?
Seketika geleng-geleng kepala saya.
Saya tak mengerti masalah aturan dan materi persidangan. Namun hakim saya perhatikan di ruang II itu, terus saja melanjutkan persidangan. Agak aneh bagi saya, sidang boleh terus berjalan walaupun petugas dari DJP, wakili negara, mewakili rakyat, bangsa, tiada.
Ketidak terwakilan rakyat itu, negara itu, terindikasi karena kebijakan menon-aktifkan segenap petugas banding pajak di DJB. Tidak berlebihan bila saya katakan, betapa naifnya sang pengambil kebijakan.
Inilah yang saya sebutkan sebagai reaktif tadi itu.
Entah mengapa kerongkongan saya seketika di Pengadilan Pajak itu kering. Saya bergerak ke ruang tengah ke warung yang sekarang kaca-kaca raknya tampak bening, bersih, dibanding pertama saya ke sana. Pada Sketsa I, saya menulis soal minuman berkaleng biru putih, maka di Sketsa ini saya sebut namanya, Pocari. Produsen Pocari kini juga salah satu perusahaan yang proses persidangan TP-nya sedang berjalan.
Kelakuannya sama. Beban biaya, dari segenap penjulan ekspor teindikasi semuanya dibebankan lokal. Sehingga Pocari yang ditenggak orang Singapura, misalnya, disubsidi oleh belulang anak negeri ini: untuk sebuah minuman yang katanya mengandung ion, meniru kandungan ada di buah kelapa. Padahal di bangsa ini di mana nyiur melambai-lambai.
Maka dengan kemasan botol plastik yang pendek dengan harga Rp 7.000, saya pun menghisap, turut menanggak “darah” rakyat sendiri.
Kejam kalimat saya?
Para produsen pengemplang pajak itu apa tidak lebih kejam terhadap bangsa ini? Anda semua dapat menjawab.
Dan jawaban panjang saya, akan bergulir terus di Sketsa ihwal transfer pricing. Dan bengaknya kita berbangsa, selama ini, segenap komponen bangsa seakan tertutup matanya soal TP ini.
Akhirnya, saya pahami pula bahwa kendati di media alternatif tulisan beredar, tampaknya disimak juga oleh pejabat di Depkeu khususnya DJP. Kalian di dalam Departemen janganlah menyalahkan pihak-pihak yang memberikan info, keterangan dan atau data atau masukan kepada saya.
Jaman sudah berganti. Keterbukaan kepada publik bukan basa-basi. Jika banyak media mainstream takut kepentingan iklannya terganggu, karena memberitakan Pocari, misalnya, peluang hilang.
Mereka di DJP kebanyakan orang baik, pekerja serius. Tak perlulah disalahkan mereka, di level staf, berpikirlah demi kepentingan publik. Mending intropeksi diri, baik sebagai Menteri, sebagai Dirjen, lebih-lebih sebagai anggota DPR, termasuk saya sendiri sebagai penulis, saking instrpeksinya, saya jamin berpuluh Sketsa TP ini pasti akan terus saya tuliskan. []
Tulisan ini dapat pula dibaca pada blog penulisnya, di: http://blog-presstalk.com