Oleh Ilham Q. Moehiddin
“Tapi apa bedanya? Tidakkah ujung selalu kembali menemukan pangkal, dan pangkal menemukan ujung?”
(halaman 28, baris 32 sampai baris 33,
Pendar Jingga di Langit Ka’bah, Naimah Herawati Hizboel
Langit Kata, Jakarta).
***
Buku Pendari Jingga di Langit Ka’bah bersampul cantik itu, oleh Hera, dikirimkannya padaku tak lama berselang setelah diluncurkan di BONDIES Café & Lounge di Kemang, Jakarta. Dia memintaku datang pada peluncuran bukunya, tapi aku tidak bisa. Ada urusan yang mendesakku untuk diselesaikan di bagian timur paling jauh Indonesia. Aku meminta maafnya, dan diberikannya.
Hati penulis perempuan ini sungguh baik. Kami belum pernah sekali pun bermuka muka secara langsung pada satu forum atau meja diskusi, belum sama sekali. Tetapi dia dengan cepat menganggapku teman baiknya, padahal kami berkenalan baru saja, melalui jejaring Facebook, pula. Aku mengundangnya menjadi bagian dari panel penulis tetap di The Indonesia Freedom Writers, sebuah perhimpunan penulis yang aku gagas sejak satu setengah tahun lalu. Sebuah perhimpunan yang bertujuan saling membagi pengalaman, ide dan gagasan dengan penulis pemula lainnya. Dia langsung setuju, tanpa ada alasan sedikit pun.
Cahaya Ka’bah Memendar Memanggil Sazkia.
Aku tak pernah menyangka isi buku itu sampai aku usai membaca bab keempat. Tadinya, aku mengira akan menemukan kisah Sazkia mengharu biru sepanjang bab hingga buku usai tuntas terbaca. Hera tiba tiba mengayun kisah Sazkia; dari flashback masa lampau gadis itu kepada hidupnya yang sekarang. Walau sempat terkejut, aku segera senang dengan gaya mengayun penulis ini pada plot. Pandai dia menyemat sambung setting, sehingga kita tak perlu gagap melihat batasnya.
Sazkia, nama gadis dalam buku itu, berkisah pedih sejak bab satu dimulai. Menjadi gadis tunggal dalam keluarganya, segera dirasakannya sebagai ujian tersendiri. Beruntung dia, dimilikinya dua orangtua yang telaten dan penuh tanggung jawab. Tak sadar dia, pada awalnya, wejangan wejangan, didikan orang tuanya itu, akhirnya menjadi dasar pijakannya ketika hidupnya berlanjut pada tangga nasib berikutnya.
Tetapi, bagaimana Sazkia menempuh pedih hidupnya tak bisa lama kau “nikmati”. Sebab, kisahnya pungkas—dan menurutku—menggantung seketika saat Anda meninggalkan bab keempat itu. Nanti akan saya beritahu apa yang aku maksud dengan kisah yang menggantung itu. Benarkah itu adalah kelalaian Hera? Atau justru disengaja olehnya, juga akan terjawab sendiri pada bab-bab selanjutnya selepas bab keempat itu.
Biar mudah bagimu, maka aku beritahu; buku ini mulai berkisah pada bab kelima.
***
Pada halaman tujuh baris ketiga, para pembaca buku ini, oleh Sazkia, akan dibawa pada stereotype kekerasan dalam keluarga yang tak berujung hukum. Apa penyiksa istri—kendati dia masih bersuamikan si lelaki itu secara sah—tidak bisa disentuh hukum?
Bagaimana posisi hukum negara bagi perempuan dalam hal ini?
Hukum normatif semestinya berlaku pada sang mantan suami. Tidak ada ruang bagi tukang siksa pada undang undang pidana kekerasan dalam rumah tangga. Jika alasannya, karena Sazkia masih istri sahnya, maka pertanyaannya; apa ada ruang dalam hukum Islam perihal kekerasan seperti itu? Tidakkah dengan jelas hukum Islam menyebut soal aniaya—terlebih terhadap kekasih hidup, sang istri—adalah juga dosa besar? Keras dan terang, Islam menyimpul hukumnya pada kasus macam itu.
Lantas, mengapa Sazkia seperti “membiarkan” kedua hukum itu berada di luar pintu rumahnya, saat aniaya berlangsung didalamnya? Sazkia ini, terasa, terlalu menerima nasib.
Lalu, di bagian mana pada kisah Sazkia itu yang menggantung? Keingintahuanku pada nasib sang mantan suami ketika berhadapan dengan hukum normatif pupus, saat tak kutemukan sedikit pun perihal itu hingga bab empat usai. Penasaran aku dibuatnya. Gemas juga mengetahui sungguh “baik” nasib lelaki tukang aniaya itu.
Rupanya Sazkia “masih tak enak hati” hendak membuka ujung nasib mantan suaminya selepas perceraiannya. Sazkia, atau Hera, menggantung tulisannya hingga tak pungkas kisah ini untuk para pembacanya. Sehingga, engkau yang membaca ini akan diliputi tanya penuh dalam benak; mengapa hakim (peradilan) hanya memutus perpisahan Sazkia saja? Tidak sekaligus mengusulkan perkara perempuan itu dilanjutkan untuk memproses tindakan biadab mantan suami Sazkia? Bukankah lebam dan siksa batin pada Sazkia terbaca pedih bukan main, maka memungkinkan bagi Sazkia, dan pemakluman dari pembaca menuntut Sazkia bertindak lebih jauh; menuntut hukum pada mantan suaminya, misalnya?
Sazkia ini, sebenarnya, hendak menegaskan stereotype macam itu. Sazkia ini hendak memperlihatkan lewat sebuah contoh, bahwa perempuan Indonesia kebanyakan—akan selalu—seperti itu. Mungkin akan mengobati rasa marah kesumat, hati remuk redam para pembaca, jika saja Sazkia membalas tindak amarah membabi buta sang mantan suami dengan hukum negara yang setimpal.
Membaca sang sang suami terpenjara, misalnya, akan bisa mengobati gejolak amarah pembaca ketika “merasakan derita” Sazkia ini. Tapi, rupanya Sazkia, tidak. Sazkia tidak membalas, Sazkia memilih bersikap syuhud.
Tetapi, mungkin akan baik jika Hera mengantar sikap Sazkia pada tulisan, tidak dengan lepas begitu saja; sepertinya Sazkia, melepas posisi perwakilannya terhadap para pembacanya. Oh, Hera… Oh, Sazkia…
Tetapi, aku keras menduga; ini disengaja oleh sang penulis. Sejak awal aku katakan perempuan ini memang piawai menyulam plot, menjalin setting. Aku mengira itu memang disengaja, sebab novel ini bergenre memoar. Mungkin dengan menelanjangi nasib si mantan suami, terasa akan terlalu vulgar. Mungkin ini caranya memancing emosi pembaca untuk lanjut ke bab berikutnya, pada bab bab perjalanan spiritualnya.
Seolah Hera ingin menegaskan kisahnya dalam buku itu; beginilah aku pada awalnya, dan demikianlah aku pada pertengahan ini. Itu membuatku bisa mengatur dan menjaga seperti apa aku akhirnya, kelak. Oh, Hera… Oh, Sazkia…
***
“Sudah kau baca Pendar Jingga di Langit Ka’bah?”
Begitulah aku menyapa sahabatku, yang dosen sastra, penggemar sanad ketauhidan itu, di suatu sore, dari balik telepon genggamku. Dia tertawa, renyah suaranya. Syukurlah, berarti dia masih sehat sehat saja.
“Waktu kau datang membawakanku sajaknya, namanya segera aku ingat. Saat di toko buku aku lihat buku itu tertera namanya, lantas aku beli. Sudah aku baca.” Sahutnya dari seberang telepon. Tak perlu kutanya dia ada di mana. Sore, aku tahu, itu dia menerima teleponku dari rumahnya; sebab suara anak kecil berteriak teriak terdengar jelas olehku. Itu anak lelakinya, usianya masih empat tahun.
“Tadinya aku hendak merekomendasikannya padamu. Tetapi karena kau sudah memilikinya, maka aku hendak meminta pendapatmu saja. Bagaimana?” Kataku lagi.
“Kau sekarang di rumah ya?” Tak langsung dijawabnya pertanyaanku. Justru aku benarkan lebih dulu pertanyaan baliknya itu. “Mirip panduan perjalanan, namun lengkap. Kalaupun ini sebuah panduan perjalanan umroh, sangat layak aku miliki. Membacanya serasa sedang ikut umroh bersamanya…hehehehe.”
“Jangan terkekeh. Bagaimana menurutmu buku itu sebagai sebuah memoar?”
“Layak. Pantas. Manusiawi. Membacanya, membagi pada kita gambaran besar hidup seorang hamba, yang benar benar menghamba. Kedekatan macam itu terhadap entitas Ilahiyah, cukup jarang ditemui. Aku justru hendak bertanya padamu; apakah rutinitas dan kesengajaan merendah hakikat sedemikian rupa itu, akan mengantarmu sedemikian dekat pada spiritualitas yang paripurna?” Kawanku itu balik bertanya.
“Itulah pintunya, sahabatku. Tidakkah kau merasakan dahsyatnya tutur buku itu ketika perempuan itu dihampiri berturut turut pengalaman spiritual yang hebat? Padanya, eksistensi ketuhanan menjadi sebuah keniscayaan. Jika dia berontak, rebelitasnya terbaca terlalu santun, menurutku. Aku mengira, Hera ini, tak menyadari ketika rindunya menjelma cinta. Cinta yang datar namun keras, pada entitas maha dahsyat. Makanya, dia dihampiri-Nya, beruntun, berulang ulang.” Jelasku padanya.
“Thasawuf-sufistik? Nyaris, menurut.” Kata kawanku itu, “seandainya, jika dia mau menyerahkan seluruh dunianya untuk akhiratnya. Maksudku, seluruhnya.”
Tegas dan kentara telaah kawanku itu. Hebat, kali ini dia tak punya selera mendebat pendapatku. Padahal, aku tahu persis kegemarannya; lebih dulu mematahkan asumsiku sebagai jalan masuk pada perdebatan yang bernas. Biar lebih liat, katanya. Pusing kepalanya kalau tidak berbantahan denganku, barangkali.
“Dare alle luce…buku yang bagus.” Katanya padaku diakhir percakapan itu.
Demikianlah bahasan kami perihal Hera dan buku Pendar Jingga di Langit Ka’bah, karya memoarnya itu. Seperti kata kawanku tadi; dare alle luce (berarti; membawa terang, dalam bahasa Italia), begitulah nilai buku itu.
Kuucapkan salam padanya dan kutitipkan salam-cium buat anak lelakinya. Aku sayang pada anaknya itu, tetapi kadang jika tak awas, jarimu akan direnggutnya, lalu digigitnya. Aku berjanji akan mengunjunginya tak lama lagi.
***
Sesungguhnya buku ini mulai bercerita pada Bab 5. Perjalanan Jiwa. Sesungguhnya penulis mulai melepas jejak pengalamannya pada kisah di bab ini. Pada bab sebelum bab 5, pesan terkait yang timbul hanyalah bahwa penulis, atas nama Sazkia ini, membuhul niatnya pada perjumpaan spiritualis; antara dia, dengan tanah suci; dengan Tuhan pemilik tanah suci; dengan Tuhan pemilik semesta; dengan Allah SWT saja.
Anda bisa membuktikan prasangka saya pada paragraf awal bab tersebut.
Mari menikmati konflik spritualis: Sazkia mulai bergulat pada konflik internal dirinya, terbaca pada bab 6, di penuturan penuturannya, doa doanya.
“Gusti Allah yang Agung, ampuni aku wahai pemeliharaku. Aku ingin menghapusnya. Menyudahi peperangan yang menyandera batin dan hatiku. Semua harus segera aku anggap tamat dan berlalu setelah aku menanggung rasa sakit yang mengiris-iris, yang telah mengubah semua persepsiku kepadanya yang selama ini menghantui benakku. Tujuh tahun yang melelahkan, cukuplah sudah. Aku ingin mendirikan sholat dan berzikir di depan pintu Ka’bah-Mu. Bersimpuh hanya untuk-Mu. Menyerahkan segalanya hanya kepada-Mu.”
Demikianlah. Doanya kecil saja, tetapi harapan untuk perwujudannya demikian besar, melampaui batas mitsal.
Permintaannya pun latif saja, tetapi harapannya selalu ma’ad jua pada Allah SWT, sang Qahhar, maha perkasa itu.
***
Buku ini beralur pendek; berkisah soal Sazkia pra remaja kemudian remaja; pernikahan pertama Sazkia; pekerjaan dan karir Sazkia; pernikahan kedua Sazkia; berakhir pada pengalaman spiritual Sazkia. Aku suka cara penulis ini mengayun plot, demikian halus.
Plotnya melompat lompat namun berkait mengikat ; plot ini diantar oleh Sazkia melalui ingatan-ingatannya pada peristiwa lampau dan kondisi terkini yang ditemuinya. Plotnya berputar pada; kehidupan Sazkia lalu pada keinginan mendekati Allah lewat Haji, pada kehidupan Sazkia lagi; kemudian pada “percintaan” dan kerinduan Sazkia pada Allah yang termanifestasi melalui pengalaman-pengalaman spiritual Sazkia.
Ini terekam pada kalimat yang terkutip di halaman 28, baris 32 sampai 33. “Tapi apa bedanya? Tidakkah ujung selalu kembali menemukan pangkal, dan pangkal menemukan ujung?”
Demikian itu intinya, ibadah itu, hidup manusia itu; berputar melingkar, berulang, mirip tawaf pada prosesi haji. Ini yang hendak disampaikan Hera, lewat Sazkia.
Dua Hal Lainnya Dalam Catatanku
Buku ini hendak berkisah tentang dua perjalanan pada satu kisah; perjalanan spiritual, dan perjalanan jism mitsali (jasmaniah). Alur kisah yang terbangun menceritakan kedua perjalanan ini sekaligus pada satu plot dan setting, dengan piawai dijalin penulisnya.
Saat sedang melakukan perjalanan umroh secara jasmaniah, pada saat yang sama Sazkia pun melakukan perjalanan rohani yang dikisahkan menakjubkan dan penuh keberuntungan yang serba kebetulan. Membaca perjumpaan demi perjumpaan Sazkia dengan aura spiritualisme, sungguh, kita akan segera berguman, “sungguh beruntungnya perempuan ini.”
Sepertinya; nasibnya yang penuh dengan pedih pada masa lalu itu, terbayar lunas dengan semua kebetulan dan keberuntungan yang menghampirinya dalam perjalanan itu.
Settingnya pun terjalin indah. Hera dengan piawai mampu melompat ringan dan indah dari penuturan soal perasaan melankolisnya ketika berada di masjid Quba, Madinah, seketika Anda dibawanya di desa Tambi, Sliyeg, Indramayu; pada sosok penari topeng Mimi Rasinah.
Demikian pula tatkala Sazkia sedang diombang ambing rasa, dimabok estetika, saat sebuah aura maha dahsyat, energi murni menghampirinya saat sholat di mesjid Nabawi, Anda akan dijalin pada pengalaman yang nyaris mirip saat Sazkia berada di sebuah mesjid Atta’awun, Puncak, Jawa Barat. Sungguh ringan lompatannya, lembut sulaman kisahnya, sehingga dua kisah pada dua setting berbeda terayun dan terbuhul cantik.
Salutku pula pada editornya; kawan Rusdi Amrullah Mathari, cemerlang dia menyunting kisah pada naskah.
***
Membaca pengalaman trance Sazkia pada saat dia dihampiri Lailatul Qadr di mesjid Atta’awun itu membuat saya teringat pada pengalaman serupa yang saya alami.
Jika Sazkia berjumpa dengan rombongan malaikat yang shalat berjamaah tepat dihadapannya, maka aku sulit menyebut mahkluk apa yang aku jumpai saat trance macam itu. Warna dan penampakannya saja berbeda, seingatku.
Tapi nanti, aku kisah pengalaman itu di lain tulisan. Silahkan Anda “nikmati” Hera ini dulu ya?
Novel memoar ini hendak mendekati tasawuf, dan ketaudihan pada Allah SWT, lewat seorang manusia perempuan bernama Sazkia. Lewat dirinya, Sazkia hendak bilang bahwa merindui, “bercinta” dengan Allah itu bisa dilakukan oleh siapa saja, setiap kalian orang Muslim.
Mendekati-Nya, sebaiknya menjadi sebuah cita-cita utama dalam konsep spiritualitas setiap orang, tetapi bahwa berakhir jatuhnya pilihan Sang Khalik pada siapa? Tentu tergantung Sang Maha Suci. Engkau bahkan tidak boleh menggugat. Engkau bahkan tidak boleh bertanya. Pungkas hakmu bahkan sebelum engkau bersedekap dalam liang tanah.
***
Banyak hal yang bisa Anda petik usai membaca Pendar Jingga di Langit Ka’bah ini. Hera membagikan banyak kisah dalam perjalanan itu; tentang kota kota suci megah, suasana masyarakat arabian, sifat lekat komunalnya, beragam pantangan ketika berada di sejumlah tempat itu. Khususnya, bagi pembaca non-wahabi, perbedaan tuntunan dan tuntutan peribadatan yang teramat kentara dengan tata cara pengikut faham Ahlul Sunnah Wal-Jamaah, Muhammadiyah, dan bahkan Syiah.
Kita akhirnya menjadi tahu, apa yang tidak boleh dilakukan saat berada di salah satu dari tempat tempat itu; masjid Quba, misalnya. Walau pun engkau Sunni, Syiah, Muhammadiyah, atau Syalafi, tidak boleh melanggar hukum Wahabi. Jika tak hirau, niscaya tongkat para Asykar barang sebentar akan mampir dipunggungmu. Minimal, engkau akan dihalau, menjauh keluar dari lokasi ibadah itu.
Mata Sazkia, atau Hera, serasa mewakili mata kita. Menerima penjelasannya soal bentuk arsitektur masjid Quba, arsitektur masjid Nabawi, dan masjidil Harram, benak kita bisa langsung membayangkan. Anda, kita, akan merasa ikut serta dalam perjalanan umroh perempuan Sazkia itu.
Lezatnya Kurma Nabi, sekaligus berjalan jalan di kebunnya; dan keajaiban Medan Magnet, seperti tak mau kita lepas kisah di penghabisan bab.
Ada nuansa lain ketika membaca buku ini, dan membuat aku mengira bahwa buku ini selain sebuah novel, include pula, mirip travel guide umroh. Semua hal yang layak berada dalam sebuah travel guide, Anda akan temui ketika membacanya; bagaimana mengurus umroh, siapa yang Anda mesti hubungi pada paket umroh plus, seperti apa akomodasi yang bakal Anda dapatkan, suasana Jeddah, Madinah, dan Mekkah; tarif beberapa hotel, toko cinderamata murah, harga dan jenis makanan di tempat tempat tertentu, bahkan siapa yang mesti Anda temui, hingga siapa yang menemani Anda sebagai pemandu, ada dalam buku ini.
Mirip sebuah paket hemat, cukup beli satu buah buku, Anda akan memperoleh sebuah novel memoar, dan sebuah travel guide. Beruntungnya Anda, bukan?
Tetapi selebihnya, bahwa buku ini memang layak adalah keseriusan penulisnya mempersiapkannya. Bahasanya rancak, padanan katanya terpilih, plot, dan setting-nya mengayun indah dan tak nampak berbekas batas pada dua bagiannya. Baik sekali.
Sejumlah nama pada endorsment buku ini terasa mewakili kualitasnya. Ada Kurnia Effendi, penulis terkenal itu. Ada Arief Joko Wicaksono, jurnalis yang juga penyair itu. Dan, ada Hadi M Djunaid, seorang wartawan kawakan yang luas relasinya.
Selebihnya, buku ini memang sangat layak untuk dibaca. Pantas pula terselip berjejer di rak buku koleksi Anda.
Tapi apa bedanya? Kau bertanya, Sazkia?
Benar Sazkia…Apa Bedanya? Bukan begitu, Hera?
Begitulah, aku telah jujur padamu. []





















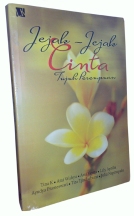










Tinggalkan komentar