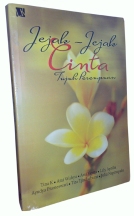Oleh Iwan Piliang, Literary Citizen Reporter
Tugas diplomat Indonesia di luar negeri, seperti saya simak di Persatuan Emirat Arab (PEA), juga cerita sosok Indonesia bekerja di Oman, bermuara: galebeh-tebeh urusan Tenaga Kerja Wanita (TKW); kabur dari majikan; di bawah umur; dilecehkan seksual; diperkosa; jatuh dari gedung; disetrika panas; sengaja menjual diri alasan terpaksa; bersuami seakan berpoliandri di negeri orang; panjang kata jika dilanjutkan. Jahanam kali laku lelaki – – termasuk saya – – mengirim perempuan mara ke manca negara. US $ 6, 615 miliar peneriman dari TKI, 2009, setara Rp 59, 5 Triliun, tiada arti apa-apa dibanding penggelapan pajak melalui transfer pricing pelaku usaha di Indonesia yang setahun melebihi Rp 1.000 Triliun. Buat apa mendidik, menggaji mahal para diplomat, jika pekerjaannya terguras arus mengurus TKW. Lanjutan Sketsa Ziad Salim Zimah yang “tertahan” 8 tahun di PEA, pulang bersama saya 16 Februari 2010: mencairkan rindu air mata darah sang ibu.
JARUM JAM menjelang pukul 00.00 di Villa, Wisma Duta, kawasan Muhammad bin Zayed City, Abu Dhabi.. Di ruang tamu Dubes RI, tiga cangkir teh dan toples kecil berisi korma hitam terhidang di atas meja. Saya, Ziad Salim Zimah, 44 tahun, dan Wahid Supriyadi, Dubes, berbincang hangat. Ziad mengucapkan terima kasih, atas bantuan yang diberikan KBRI. Pukul 02.00 dinihari itu, 16 Februari 2010, Ziad direncanakan dapat terbang pulang.
Walaupun tampak tersenyum, saya menangkap kekuatiran di wajah Ziad. Tiket pesawat, dokumen pencabutan seluruh berkas kasusnya di pengadilan, baik perdata dan pidana, termasuk bukti pencabutan black list di kepolisian, juga surat keterangan scanning retina mata di imigrasi Dubai, semuanya lengkap – – memakan tempo sebulan kami urut pengurusannya bersama pihak pihak KBRI.
“Ya Ziad, selamat, Anda akhirnya malam ini dapat pulang, atas upaya keras semua pihak yang membantu. Jadikanlah kasus ini sebagai pengalaman berharga, mari menyambut hari esok lebih baik, salam saya untuk keluarga “ ujar Wahid.
Kalimat Wahid bak seorang bapak, tapi tak mengubah kecut di wajah Ziad. Ziad baru sedikit terhibur, ketika kemudian datang Hannan Hadi, Sekretaris III, Protokol dan Konsuler KBRI, yang turut menemani kami ke lapangan terbang. Itu artinya, kami mendapatkan pengawalan hingga ke airport. “Untung ada Pak Hannan, kalau tidak jika nanti ada apa-apa lagi di airport bagaimana?” kata Ziad.
Sekadar menunggu waktu, pembicaraan di ruang tamu itu bergulir kembali ke soal TKW. “Coba Anda bayangkan, jika kami mengurus terus permasalahan TKW, kapan kami membangun citra baik negeri kita, kapan kami harus melakukan lobby mendatangkan investor, misalnya?” tutur Wahid.
Setiap bulan mendekati angka 100 orang TKW yang harus ditampung di KBRI. Manca ragam masalah. Urusan gaji belum dibayar majikan, dipukuli, hingga dimaki-maki. Untuk kasus dimarahi, pihak KBRI kesulitan menghadapi. Bisa jadi, majikan marah karena sang TKW memang datang dengan ke-awami-an; alias tembak langsung dari ndeso, memakai mesin cuci saja kagok, misalnya.
Lebih mengenaskan diperlakuan perkosaan.
Bila di Sketsa PEA I, saya deskripsikan soal Santi, lugu, di bawah umur, diduga tak paham arti kata: perkosa. Berbeda dan Laksmi, sebut saja namanya demikian. Saat saya temui di KBRI Abu Dhabi, mengaku sudah bersuami. Sosok wanita 35-an tahun itu, diperkosa oleh anak majikannya. Derita kemiskinan di kampungnya di Jawa Tengah, uang pendidikan mahal dan kesehatan selangit, telah “memisahkan” keluarganya. “Kadang bisa pulang sekali setahun, kadang dua tahun sekali,” ujar Laksmi.
Bisa Anda bayangkan perih luka hati sang suami, jika mengetahui derita sang isteri. Saya tentu tak perlu bertanya kepada Anda, para pria, jika isteri Anda diperkosa, adik perempuan, atau saudara diperlakukan demikian? Saya pastikan darah kalian bergelegak mendadak sontak!
Apa yang dicari mara ke negeri orang jika kenyataan hidup demikian?
Maka menjelang jarum jam berdentang 12 kali di malam itu, ingatan saya melayang ke Depnaker, ada pula badan add-hoc yang dibentuk oleh negara di era reformasi ini bertajuk BNP2TKI: kedua badan ini, plus para PJTKI, dengan bangga mengatakan perolehan devisa dari TKI, terutama TKW nomor dua setelah Migas.Pada 2009 negara menerima US $ 6,615 miliar ( Rp 59, 5 Triliun) devisa dari TKI.
TKI dikatakan pahlawan devisa. Jika fakta di lapangan berbeda dengan yang didengungkan, tidak berlebihan saya mengatakan bahwa bangsa ini menipu dirinya sendiri dengan riang gembira sengaja. Lebih tak berperi lagi, sesungguhnya penerimaan negara dari sektor lain tidak terurus, dari penggelapan pajak melalui transfer pricing, misalnya, diduga lebih Rp 1,.000 triliun setahun, dilakukan para pengusaha Indonesia, termasuk BUMN. Ke mana negara?
Terpikir juga di benak saya malam itu. Bisa jadi kepahitan hanya mendera para TKW yang di Timur Tengah saja. TKW di Hongkong, misalnya, banyak kisah sebaliknya, lebih manusiawi hidupnya?
Namun dugaan saya lebih baik para TKW di Hongkong itu di luar dugaan pula. Adalah Nova Riyanti Yusuf, akrab disapa Noriyu, sosok penulis tiga buah buku novel ini adalah anggota komisi 9 DPR, salah satu termuda di Partai Demokrat. Saya berjumpa dengan Noriyu pada 18 Februari 2010, di DPR saat Fraksi Demokrat menerima Ziad dan kaluarga di Lantai 9, Gd, Nusantara I.
“Ada tiga kelompok TKW yang saya lihat di Hongkong, “ Noriyu melanjutkan, “Pertama berpakaian tomboi, lelaki abis, kedua feminin dan seksi abis, rok mini menantang.” Laku lesbian menjadi trendi di TKW di Hongkong. Urusan laku hubungan intim itu, di Abu Dhabi saya seakan mendapatkan jawab, sekaligus menonton teater romansa hidup.
Mengiriman TKW sekaligus melawan kodrat Tuhan. Bayangkan mereka yang sudah menikah harus berpisah dengan pasangan. Bagaimana pula kebutuhan batin harus mereka penuhi? Sehingga, jika bukan diperkosa, hubungan persebadanan suka sama suka menjadi biasa.
Macam itulah para TKW kita berarakan nasibnya di luar negeri . “Suatu hari saya pernah mengunjungi penjara. Di sana saya bertemu para TKW yang berbuat susila, diantaranya. Saya tanya kok kamu begitu? “ tutur Wahid pula, “Ya gimana Pak, habis cowok itu ganteng-ganteng kayak di film India.!”
Wahid geleng-geleng kepala mendengar jawaban TKW yang dihukum karena berzina. Masih untung penjara di Abu Dhabi tak macam di Indonesia, makanan terjamin, lingkungan penjara sehat. “Mereka malah jadi gendut-gendut,” ujar Wahid.
“Kejenakaan” TKW yang ditemui Wahid itu belumlah klimaks. Suatu hari stafnya kedatangan seorang TKW melaporkan dirinya diperkosa. Karena faktor surat-suratnya lengkap, PJTKI yang mengirimnya jelas, umurnya dewasa, maka dilaporkan ke polisi dan diotopsi.
Kongklusi otopsi?
“Looks comfortable.” Artinya tidak terdapat luka vagina yang dipaksa.
Staf KBRI yang bercerita ke saya berurai air mata tawa, geli menceritakan pengalaman ini.
Ada pula TKW di KBRI yang ditanya kamu diperkosa?
“Ia Pak!”
Berapa kali?
“Ada lima kali!”
Di waktu berbeda?
“Iya Pak?!”
Lain di PEA, lain pula di Arab Saudi. Menurut Noriyu, anggota DPR kita itu, kini ada 20.000 TKI asal Indonesia yang over stay di Jedah.. “Saya ke Jeddah, melihat mereka berserakan di bawah-bawah kolong jembatan, mereka memasak di sana,” ujarnya. Kisahnya ini belum lama.
Noriyu menyaksikan di Oktober 2009. Di kelebihan masa tinggal itu, seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi memulangkan? Agaknya volume manusia sudah demikian besar, mereka masih di sana.. Hingga kini belum tercapai kesepakatan kedua negara bagaimana cara memulangkan ke-20.000 manusia itu. “Dalam waktu dekat akan ada agenda pembiacaraan lagi soal over stayer oleh kedua negara,” kata Noriyu.
Yang pasti, simak data ini: dari 20.000 ribu orang itu, sekitar 10% -nya adalah pernah tercatat menjadi Perkerja Seks Komersial (PSK) di tanah air. Dan saktinya lagi, hampir 1.000 dari mereka mantan narapidana. Jika mantan napi, mantan PSK, ikut berhamburan ke negeri orang, bagimana dengan pertanggung-jawaban moral mereka?
Mereka kini mengalami nasib macam Ziad, belum bisa pulang di negeri seberang, dan itu terjadi berulang-ulang, tak tahu lagi lema yang harus saya tuliskan, melihat negeri ini yang sesungguhnya kaya raya, tetapi anak negeri berjuang belang-belentang.
WAKTU SEDIKIT lagi pukul 00.00. Mengingat dokumen Ziad yang mesti diurus di bandara, kendati penerbangan Etihad yang akan membawa kami pulang take off pukul 02.00, kami pamit kepada Wahid Supriyadi, Dubes. Saya jabat tangannya, sambil mengucapkan janji, sepulang ke tanah air, sebatas bisa, minimal melalui tulisan, akan melakukan upaya agar Indonesia ini tidak lagi mengirim TKW-nya ke luar negeri, Kendati berkerja di negeri orang adalah hak, akan tetapi bila TKW yang dikirim dipastikan mudaratnya lebih tinggi dari manfaat. Maka, atas dasar itulah saya lebih hormat kepada India, Pakistan, Bangladesh bahkan Nepal, tidak mengirim perempuannya menjadi babu.
Dua hari sebelum saya pulang Tuhan sekaan mengantar contoh solusi kepada saya. Saya seakan mendapatkan jawaban. Adalah Untung Wiyono, Bupati Sragen, Jawa tengah, Ia berkunjung untuk misi dagang ke PEA. Ia melakukan presentasi di KBRI Abu Dhabi. Saya diberi kesempatan Wahid, Dubes, menyimak. Di luar dugaan saya, daerah yang bersemboyan bebas pengemis, bebas pengasong, pohon tanpa paku, tanpa ada pemboman ikan ini, sudah sejak 2003 tidak lagi mengirim TKW ke luar negeri.
Kok bisa?
Hampir setiap malam sebelum tidur di PEA, saya selalu bertanya dalam hati, bagaimana solusi lapangan kerja, agar Indonesia terbebas mengiriim TKW ke luar negeri. Eh, jalan Tuhan, telah mengantarkan saya bertemu contoh nyata di PEA.
Di kesempatan makan pagi bersama Untung dan Wahid, saya mendapatkan penjelasan, bahwa jika suatu hal memang diniatkan, pasti ada jalan. “Kami memiliki techno park untuk mendidik tenaga kerja berpengetahuan, terdidik. Kredit usaha kecil kami maksimum hingga Rp 500 juta tanpa agunan dijalankan oleh Pemda langsung,” ujar Untung. Sehingga kini, praktis tak ada warga yang menganggur.
“Bahkan pegawai negeri di luar jam kerja, saya suruh jadi pengusaha,” ujar Untung.
Entah mengapa saya terlambat tahu, dan baru dibukakan telinga setelah jauh di negeri seberang. Karenanya saya berjanji kepada Bupati Sragen itu untuk di suatu kesempatan bertandang dan dapat membuat literair untuk Anda, mengapa Sragen bisa tak lagi mengirim TKW mara ke manca negara bekerja.
TURUN dari mobil hendak memasuki terminal bandara di pukul 00.15 itu, udara terasa dingin menyapa kulit. Di mobil hingga turun bandara itu, Ziad saya perhatikan tak bicara,. Ia menjawab satu dua kata saja pertanyaan saya. Misalnya, apa surat, paspor sudah dikantung? “Sudah,” ujarnya.
Kami ditemani supir staf KBRI Syamsu Rizal, akrab disapa Jali. Sosok inilah di waktu silam yang menjadi supir pribadi, Saleh Alkatiri, adik ipar yang memperkarakan Ziad. “Jali pula dulu yang memberikan paspor saya ke Saleh, sehingga Saleh dapat menahan paspor saya,” tutur Ziad kepada saya.
Saya tegaskan ke Ziad, kaji lama tak perlu dikenang. Urusan baru, bak kata Wahid, hari esok menjadi lebih penting. Apalagi malam itu, Jali, menemani kami sudah bak pejabat RI, yang kalau bertugas ke luar negeri acap merepotkan staf KBRI, harus diantar dan ditemani hingga masuk ke ruang boarding bandara.
Benar saja, di migrasi saya dengan mudah lewat. Tidak demikian dengan Ziad. Setelah melihat surat dan paspornya., ia diminta menemui polisi di ruangan sebelah migrasi. Saya melihat Ziad dari jauh. Sebagaimana diperkirakan Ziad, untung ada Hannan Hadi. Pejabat KBRI ini kemudian berdiplomasi. Rupanya Ziad harus dicek ulang retina matanya.
Kala itu saya sudah bertekad dalam hati. Jika Ziad belum juga bisa pulang, saya akan tunda terbang, biarlah dua tiket yang sudah kami beli hangus. Rasa penasaran, senang berkecamuk kesal berurusan legal di PEA: seberapa panjang lagi urusan di negeri yang dibangun oleh Alamrhum Syeh Zayed, yang dicintai rakyat itu?
Untunglah setengah jam kemudian Ziad bisa lolos dari imigrasi.
Alhamdulillah, Puji Tuhan.
Serta merta wajah Ziad saya lihat masih tegang.
“Saya baru akan tenang kalau pesawat sudah take off,” uajr Ziad.
Saya hibur Ziad dengan mengajaknya membeli sekotak dua kotak coklat, sekadar ole-ole.
DI RUANG tempat boarding Etihad dengan penerbangan EY 472 itu, mata kami kembali tertumbuk dengan ratusan TKW. Mereka umumnya berpakaian lusuh. Satu dua ada yang rapi berjins ketat berselendang. Padanan warnanya serasa kurang pas, merah diadu hijau, selendang hitam. Bibir berggincu merah menyala.
Para TKW itu ada yang transit dari Mesir, Oman, Arab Saudi. Salah seorang tampak berjalan tertunduk seperti orang sakit. Ia ditemani oleh staf darat Etihad yang tampaknya wanita Filipina. Ia diminta duduk di ruang tunggu, tetapi begitu pendamping crew darat Etihad bergerak, sosok TKW itu pun ikut berjalan. Wajahnya ketakutan. Saya enggan bertanya.
Begitu pengumuman penumpang dipersilakan naik pesawat, mereka berebutan, tidak mengerti antri. Logika saya, setelah mereka di negeri orang, seharusnya mereka paham bahwa antri itu salah satu budaya, yang menandakan beradabnya sebuah bangsa. Saya perhatikan satu dua orang bule yang satu penerbangan dengan kami, tersenyum kecut.
Setengah jam kemudian barulah kami naik pesawat. Sambil bercanda saya minta Ziad mencubit jangat tangannya. Apa bukan mimpi pulang?
“Saya belum tenang.”
“Pengen rasanya mendorong pesawat ini agar cepat take off,” ujar Ziad.
Sambil menunggu pesawat take off saya berusaha menyapa seorang pria di kanan bangku kami. Ia rupanya bekerja di sebuah perusahan migas di Oman, tepatnya di Muscat. Di belakangnya seorang ibu paruh baya, TKW asal Karawang. Ia mengaku pulang karena tidak tahan bekerja membersihkan WC di kota Salalah, 900 km dari Muscat, ibukota Kesultanan Oman.
Kota Salalah adalah kota tua unik di tepi pantai kawasan Timur Tengah. Di sana dikenal dua musim; panas dan 4 bulan hujan gerimis. Kawasan di sana berada di ketinggian dan hijau. Di saat wilayah Timur Tengah lain didera panas hingga mencapai 50 derajat celcius, Salalah kian sejuk di bulan Juni hingga September. Di Salalah dimakankan Nabi Ayub, salah satu Nabi yang tertera untuk diimani sesuai amanat Rukun Iman Umat Muslim.
Selama di udara 8 jam itu, sepertiga waktu saya habiskan mendengar cerita soal tenaga kerja di Oman. Urusan TKW menjual diri macam yang saya temui di dua restoran Indonesia BDG dan SR di malam hari di Abu Dhabi, rupanya, di Oman lebih parah lagi.
“Para supir taksi di Oman, sudah paham kalau TKW kita itu, maaf, citranya bisa memang bisa dipakai,” ujar Burhanudin, sebut saja demikian. Sosoknya mengaku dulu pernah pula bekerja di PJTKI. Ia merasa bersyukur kini bisa hijrah dan bekerja di bagian purchasing sebuah oil company di Muscat.
“Nanti kalau ada waktu di bandara Jakarta, Mas ikuti saja, banyak dari TKW yang sudah menyiapkan uang untuk pungutan ini dan itu. Dan, maaf, ya, bahkan mereka ada juga menyiapkan bandannya.”
Masya Allah!
“Suatu hari ada kenalan saya berlibur dari Muscat ke Jakarta. Ia bingung melihat wanita Indonesia yang berbeda jauh dengan apa yang mereka lihat di Oman,” tutur Burhanudin.
Saya lalu terlelap setelah meminta segeals red wine kepada pramugari Etihad yang ramah. Film Transformer, salah satu yang saya pilih dari 73 DVD yang tersedia, saya memencet touch screen. Mata saya nanar. Mata Ziad masih terang menerawang. Entah apa yang sedang bekecamuk di dadanya?
Menjelang terlelap, tak terasa air mata saya mengalir. Dua orang wanita seakan menyapa malam di ketinggian 33 ribu kaki itu. Pertama ibuku, ia telah berpulang pada November 2009 lalu. Kedua wajah tersenyum ibu mertuaku, juga sudah meningglkan kami sejak 5 tahun silam. Keduanya sosok wanita yang kukagumi kesabarannya.
Ibu mertuaku tercatat sebagai karyawan teladan di Deppen – – kini Depkominfo – – kami anak menantunya baru tahu setelah seorang pejabat Depkominfo datang melayat, menyampaikan ucapan duka di hari berkabung, bahwa yang kami shalatkan adalah karyawan teladan, ibu teladan, wanita terhormat, bukan bak TKW yang bersebutan entah untuk apa ke negeri orang?
Untuk uangkah? “Gaji saya kecil, saya mau cari kerja di Jakarta saja, sebab kalau pulang ke Karawang malu sama tetangga,” kata ibu paruh baya di kanan saya tadi.
Ketika terbangun, sinar matahari sudah menembus jendela pesawat, persis menusuk pandang mata. Saya sapa Ziad, sebentar lagi kita mendarat. Baru siang itu saya lihat wajahnya senang. Delapan tahun lamanya ia dominan berhadapan dengan tembok: takut ke luar rumah, kuatir ditangkap polisi, karena urusan nasibnya yang diperkarakan namun tak terbukti bersalah itu.
Etihad EY 472 itu mendarat pukul 14.00. Para penunmpang bergerak berdiri mengemasi barang bawaan. Namun mendadak sontak, suara pramugari berbahasa Indonesia mengumumkan sesuatu.
“Penumpang diminta duduk kembali, untuk sekitar sepuluh menit menunggu polisi menjemput seorang penumpang!”
“Aduh Pak Iwan, pasti saya?”
Wajah Ziad pucat-pasi.
Saya duga tangannya dingin. Saya hibur Ziad: Jika sudah di Jakarta, bukan Anda yang akan ditangkap, tetapi saya – – saya menjawab sekenanya demi menenangkan Ziad.
Tak lama kemudian, 4 orang polisi bandara yang bertugas untuk Etihad berpakaian biru-biru masuk ke kabin pesawat.
Muka Ziad pucat.
Darah seakan pergi dari bibirnya!
Rupanya, polisi itu menghampiri seorang pria berwajah Arab seperti Ziad. Ia duduk tiga baris di kanan belakang kami. Ketika dalam perjalanan, pria itu merokok. Ia sempat ditegur penumpang lain, tetapi malah melawan. Sempat ditegur pramugari Etihad tapi tak terima. Begitulah, di saat mendarat, diringkus polisi bandara ganjarannya.
“Alhamdulillah, “ kata Ziad plong! [] (bersambung)
Tulisan ini dapat pula dibaca pada blog penulisnya, di: http://blog-presstalk.com